kolonial
berfikir yang diajarkan oleh para filsuf dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menghasilkan
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa kesejahteraan bagi manusia. Alam dan
manusia itu sendiri merupakan sumber inspirasi berfikir manusia mencari kebenaran dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya Dengan bertitik tolak pada manusia,
cara pandang manusia terhadap alam dan dirinya sendiri mengantarkan manusia kepada cara berfikir
monisme dan dualisme , Kelak cara berfikir monisme dan dualisme tersebut
dikembangkan menjadi metodologi kuantitatif dan kualitatif. Filsafat Ilmu dinyatakan bahwasanya metodologi kuantitatif yang menganut nilai
kebenaran tunggal bertolak dari cara berfikir monisme melihat hukum-hukum alam yang berlaku
universal, sedangkan metodologi kualitatif yang menganut nilai kebenaran jamak bertolak dari cara
berfikir dualisme melihat fenomena alam berdasarkan sudut pandang manusia yang kompleks.
Dibidang arsitektur, kelahiran arsitektur modern sebagai produk gerakan modernisme di Barat
yang berawal dari kebangkitan ilmu pengetahuan (renaissance) melawan dogma-dogma gereja
zaman kegelapan (dark ages). Semangat kebebasan ilmu pengetahuan dari atribut teologi yang saat
itu identik dengan keberadaan gereja juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan filsafat berfikir
manusia yang ingin memurnikan kembali manusia dari dogma gereja yang dianggap membelenggu
dan hanya berpihak pada golongan tertentu. Beberapa filsuf yang berpengaruh pada masa ini
diantaranya adalah Leibniz (1646-1716), John Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753), dan lainlain. Selanjutnya arsitektur sebagai simbol melepaskan dirinya dari ornamen-ornamen yang dianggap
tidak fungsional dan membebani bangunan itu sendiri . Di Indonesia, semangat modernisme hadir seiring dengan kedatangan kolonialis ke tanah
Hindia Belanda (sebutan Indonesia pada masa itu). Penemuan heliosentris dan bentuk bumi yang
bulat oleh Copernicus dan Galilleo mendorong para pelaut menjelajahi dan mencari sumber daya
alam yang dihasilkan bumi dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumalyo
(2005) selanjutnya menyatakan bahwasanya adanya Benteng Belanda di Indonesia merupakan wujud
arsitektur Eropa yang pertama didirikan sebagai simbol dari keinginan Belanda melalui serikat
dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk meneguhkan kekuasaan monopoli
perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas dagang yang memberikan keuntungan
besar bagi Eropa. Seiring waktu arsitektur kolonial digunakan dan dikembangkan sebagai simbol
peneguhan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda di berbagai bidang kehidupan masyarakat
bahwasanya penerapan arsitektur
kolonial dan simbol-simbolnya dimaksudkan sebagai pembeda status sosial antara warga Eropa dan
kaum bangsawan dengan warga pribumi. bahwa
perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial
dan lingkungan Hindia Belanda yang berbeda dengan Eropa, mereka melakukan adaptasi dan
akulturasi dengan arsitektur lokal untuk menciptakan arsitektur yang lebih sesuai untuk mereka
tinggali di Hindia Belanda. Arsitektur Indis selanjutnya merupakan istilah yang kerap digunakan
untuk menyebutkan arsitektur kolonial Belanda hasil proses adaptasi dan akulturasi tersebut.
Pada tulisan ini akan dibahas bagaimanakah pengaruh perkembangan filsafat keilmuan barat
terhadap perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga kedepannya diharapkan
dapat dijadikan salah satu landasan berfikir bagi peneliti arsitektur maupun masyarakat awam dalam
mengamati keberadaan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia secara lebih tepat dan terperinci.
Meskipun arsitektur kolonial di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan arsitektur yang ada di
Eropa, namun pengaruh alam dan budaya yang berbeda tentunya akan melahirkan cara berfikir
arsitektur yang berbeda juga. Hal tersebut tentunya akan menghasilkan keragaman dan kekhasan
arsitektur kolonial sebagai bagian tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan arsitektur di
Indonesia.Sejarah filsafat barat mencatat kolonialisasi paling tua dilakukan oleh Bangsa Sparta atas
Athena. Hal tersebut bertujuan untuk melegitimasi bahwa Bangsa Sparta lebih unggul jika
dibandingkan dengan Athena yang dikenal telah maju pola berfikirnya dan telah memiliki sistem
kenegaraan yang melembaga ,. Dengan begitu maka sudah sejak lama kolonialisasi
identik dengan keinginan untuk menaklukan bangsa atau kelompok masyarakat lain dan merebut
identitasnya. Hal ini tentunya merupakan tujuan dari pendekatan berfikir kategori, dimana pada
akhirnya terdapat label antara bangsa yang unggul dan bangsa yang tidak unggul.
Apa yang dilakukan oleh Bangsa Sparta terhadap Athena tersebut ternyata mempengaruhi
Plato untuk menciptakan konsepsi negara ideal yang diberi nama Negara Utopia
Selanjutnya konsep tersebut selalu menjadi rujukan beberapa pemikir penting dari masa Aristoteles,
hingga Karl Marx ,. Adapun intisari dari Konsep Negara Utopia adalah
penciptaan institusi yang selanjutnya disebut dengan negara, yang bertujuan untuk menciptakan
kebahagiaan bersama melalui serangkaian penaklukan untuk menerapkan kepatuhan aturan yang
diberikan oleh kaum bangsawan terhadap rakyat jelata. Jelaslah bahwasanya untuk dapat
membedakan golongan bangsawan atau tidak bangsawan diperlukan pengakuan bahwasanya ada
golongan yang lebih unggul dan ada kesediaan untuk mengikuti aturan dari yang lebih unggul.
Selanjutnya kolonialisasi berkembang dengan berbagai motif. Pada masa Helenisme misalnya,
Philipos dari Makedonia menaklukkan Yunani untuk menguasai filsafat, ilmu pengetahuan serta
aturan-aturan negara dalam rangka untuk mengklaim bahwasanya ia adalah Rasul-Raja (wakil Tuhan
untuk memerintah). Ia kemudian melanjutkan penaklukannya ke daerah lain dan menerapkankan
kelembagaan negara Yunani yang telah ditaklukkannya pada wilayah taklukan sebagai simbol
eksistensi. Bahkan ia juga membangun beberapa bangunan dengan menggunakan gaya arsitektur
Yunani sebagai simbol fisik. Penulis berpendapat bahwasanya inilah awal mula arsitektur dapat
dipergunakan sebagai simbol atau identitas kolonialisme.
Pada zaman Epikurean dan Stoisme, kegiatan berfilsafat berkembang pesat dari sebelumnya
dan mampu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Lahirnya berbagai macam ilmu
pengetahuan berarti melahirkan spesialisasi dalam berfikir yang kemudian mendorong lahirnya
materialisasi ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mendapatkan kesejahteraan dan pengakuan dari
masyarakat . Dengan demikian maka muncul gejala simplifikasi filsafat agar lebih
mudah dirasa secara indrawi. Lebih lanjut jika filsafat dinilai dengan suatu hal yang bersifat indrawi
maka tentuya dapat ditukar atau dimiliki dengan barang lain yang indrawi pula. Dari sini kemudian
muncul kategorisasi pengguna filsafat, dengan lahirnya kaum skeptis dan sinis ,
Kedua kaum ini selanjutnya selalu muncul dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Kaum
Skeptis adalah mereka yang hasil pemikirian ataupun ilmu pengetahuannya diapresiasi oleh
masyarakat, dan mendapatkan kesejahteraan atasnya. Sebaliknya mereka yang pemikiran ataupun
ilmu pengetahuannya tidak diapresiasi masyarakat akan digolongkan sebagai kaum sinis yang
merasa dimarjinalkan karena tidak mendapatkan kesejahteraan atasnya.
Kategorisasi Kaum Skeptis dan Sinis menjadi mencapai belahan Dunia Timur melalui
penaklukan atau kolonialisasi Barat yang disimbolkan dengan semangat 3G (Gold, Gospel, Glory)
yang didengungkan oleh kerajaan dan gereja Eropa. Semangat 3G tersebut mempertegas dikotomi
keberadaan kaum Skeptis yakni penjajah dan kaum Sinis yang diwakili oleh pribumi. Menariknya
keberadaan Kaum Skeptis dan Sinis tidak muncul pada saat penyebaran Islam, karena pemikiran dan
ilmu pengetahuan Islam disebarkan tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan, dan Islam tidak
mengenal penaklukan untuk menyebarkan ideologinya. Hal ini salah satunya dapat terlihat pada
peradaban Islam di Andalusia .Untuk mengukuhkan identitas sebagai kaum yang lebih unggul di tanah jajahan (setidaknya
menurut orang-orang Barat sendiri), mereka tetap memaksakan pemikiran mereka sendiri alih-alih
menyesuaikan dengan yang telah ada di Timur. Mereka menerapkannya diberbagai bidang
kehidupan termasuk arsitektur sebagai simbol pengukuhan jati diri. Selanjutnya hal tersebut semakin
menjadi dikarenakan mereka kemudian berhasil menguasai sumber daya alam yang ada sehingga
orang-orang Timur terpaksa mengikuti aturan-aturan yang didasarkan pada pola pikir orang-orang
Barat. Dalam konteks ini, arsitektur dan perancangan kota merupakan wujud material dari pemikiran
yang bertujuan untuk menjadi simbol pengukuhan,
Kelak di akhir masa kolonialisasi akhirnya terjadi kompromi antara Barat dan Timur karena faktor
perbedaan lingkungan dan iklim yang mau tidak mau harus diselesaikan oleh orang-orang Barat.
Pengaruh Perkembangan Filsafat Terhadap Kegiatan Kolonialisasi
Kolonialisasi dimulai pada masa Yunani Kuno, dengan adanya penaklukan Sparta terhadap
Athena, kode moralitas dan cara hidup bermasyarakat berkembang dengan tidak menempatkan
adanya raja sebagai penguasa. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya kesejahteraan
hidup diperoleh dari ketersediaan sumber daya. Situasi inilah yang kemudian menjadi awal dari
kolonialisasi yang bermotif pengumpulan sumber daya alam. Dalam keadaan yang tenang,
rasionalitas manusia Yunani Kuno dapat tumbuh dan berkembang melahirkan berbagai macam
filsafat. Tujuan dari berbagai macam filsafat pada masa Yunani Kuno adalah menghadirkan
kebahagiaan yang identik dengan rasa sejahtera manusia akibat terpenuhinya sumber daya. Adapun
ciri filsafat yang lahir pada masa ini adalah religius dan mistik. Di sisi lain, penaklukan Athena oleh
Sparta didasarkan atas keinginan untuk membuktikan kode moralitas dan cara hidup siapa yang
paling unggul. Uniknya, setelah penaklukan terjadi justru kedua kode moralitas dan cara hidup
tersebut berdampingan dan pada akhirnya melahirkan kasta-kasta warga yang lebih beragam. Dari
fenomena di atas dapat diketahui bahwasanya meskipun terdapat kategori yang berbeda (Sparta dan
Athena), filsafat mengajarkan untuk lebih mengutamakan rasionalitas, mencapai “nilai bersama”
yaitu kebahagiaan hidup.
Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, filsafat Yunani Kuno diantaranya
menghasilkan mazhab epikurean dan stoisme sebagai cara memperoleh kebahagiaan hidup melalui
proses berfikir. Filsafat tersebut semakin meluas di daratan Eropa pada masa Milesian. Melalui 5
(lima) tokoh utamanya yaitu Thales, Anaximenes, dan Anaximander, Phytagoras, dan Heraklitus,
mereka mengajarkan bahwasanya segala sesuatu memiliki unsur utama alam yang dapat diketahui
dengan melakukan pengamatan atau pengalaman empiris (Hadiwijono, 1980). Kelak pada akhir
masa dark ages (jaman kegelapan) hingga modernisme awal, kemajuan ilmu pengetahuan yang
berbasis empirisme mampu melahirkan teknologi yang semakin memudahkan manusia melakukan
segala urusannya, dan hal ini semakin mempertegas posisi kaum Skeptis dan Sinis (Russell, 2007).
Penulis berpendapat bahwasanya skeptisme dan sinisme melahirkan dikotomi masyarakat
beradab dan tidak beradab menurut persepsi pemikiran orang-orang Barat dan hal ini menjadi label
golongan masyarakat pada masa kolonialisme. Kaum skeptis dicirikan sebagai pemilik ilmu
pengetahuan maupun modal yang mampu menggerakkan masyarakat dan mendatangkan
kesejahteraan. Pemikiran mereka cenderung didasarkan atas kesadaran individual (liberal) dalam
melihat permasalahan hidup, serta menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi untuk
mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu mereka sering kali dicirikan sebagai kaum yang
materialistik, pragmatis, namun demikian mereka cenderung mampu berfikir secara prosedural.
Sebaliknya kaum sinis berusaha mencapai kebahagiaan secara komunal, sehingga setiap
permasalahan dikaji secara holistik dan mereka mencoba melepaskan diri semaksimal mungkin dari
materialitas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu mereka sering kali dicirikan sebagai kaum yang
spiritualistik, setia, dengan ciri khas berfikir secara holistik. Kaum skeptis dalam konteks
kolonialisme di dunia Timur termasuk Indonesia dapat diidentikkan sebagai kaum penjajah yang berorientasi pada kesejahteraan negara berbasis individualisme yang berpedoman pada aturan-aturan
yang prosedural, sedangkan kaum sinis identik dengan rakyat biasa (pribumi) yang berorientasi pada
kebahagiaan sederhana. Kolaborasi keduanya merupakan tujuan dari institusi negara saat itu (Hindia
Belanda) untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dengan cara mengeksploitasi serta mengolah
sumber daya dengan cara-cara pemaksaan yang diterapkan oleh penjajah terhadap pribumi.
Dalam konteks yang lebih luas, kaum skeptis dan kaum sinis merupakan representasi dari
penguasa dan yang dikuasai. Keduanya selalu ada dan bertukar peran meskipun filsafat pemikiran
manusia terus berganti. Contohnya dapat dilihat pada akhir zaman kegelapan Eropa menuju zaman
moderisme yang ditandai oleh gerakan renaissance. Kaum skeptis yang semula terdiri atas golongan
bangsawan dan gereja bertukar peran dengan golongan pedagang dan pengusaha pada masa
renaissance hingga modernisme. Munculnya filsafat kenegaraan Machiavelli di akhir masa
kegelapan juga mendorong lahirnya konsep negara yang akomodatif terhadap kaum pedagang. Hal
ini dikarenakan dahulu pihak gereja dan kerajaan mengambil sumber daya rakyat hanya untuk
dihambur-hamburkan, sedangkan pedagang setidaknya membeli dari rakyat. Kaum pedagang merasa
semakin didukung setelah penemuan sains kebumian terutama mengenai penggambaran bentuk bumi
oleh Copernicus, Kepler, Galilleo, dan Newton. Penemuan itu mendorong semangat manusia untuk
menjelajah bumi demi mencari sumber daya alam yang selanjutnya akan diperdagangkan dan
mengisi kas negara melalu pajak. Sehingga situasi yang berkembang pada saat ini adalah sinergitas
antara kerajaan, sains, dan kaum pedagang.
Selanjutnya terdapat 2 golongan bangsa Eropa yang melakukan perjalanan keliling dunia yaitu
kaum kontra reformis bernuansa Gereja Katholik yang dipelopori oleh Bangsa Portugis dan Bangsa
Spanyol, serta kaum reformis bernuansa gerakan Protestan yang dipelopori oleh Jerman, Belanda,
Inggris, dan lain-lain (Russell, 2007). Hal tersebut dapat kita lihat pada banyaknya ekspedisi
menjelajahi dunia yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad ke 16 dan 17 dalam rangka mencari
sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Diantara ekspedisi tersebut sampai ke Indonesia melalui
Belanda dan berhasil mendapatkan komoditas rempah-rempah. Rasa puas mendapatkan keuntungan
ekonomi kemudian menarik Belanda untuk kembali pada abad ke 18 dengan keinginan memonopoli
perdagangan. Dari sinilah kemudian muncul kolonialisme yang dicirikan dengan praktek pemaksaan
aturan yang beragam rupa oleh diterapkan oleh orang-orang Belanda terhadap pribumi di Hindia
Belanda.
Seperti pisau bermata dua, selain menghadirkan derita, kolonialisme menghadirkan
modernisme Eropa di Dunia Timur termasuk Indonesia. Pemikiran filsuf-filsuf Barat yang
mendorong munculnya modernisme di Eropa dapat dirasakan pula di Hindia Belanda melalui gaya
hidup yang diterapkan orang-orang Eropa. Alih-alih beradaptasi terhadap sendi-sendi kehidupan
masyarakat Hindia Belanda, modernisme justru kembali melahirkan berbedaan perlakuan
berdasarkan golongan sebagai akibat dari perkembangan filsafat di jaman modern yang medorong
sains lepas dari sistem kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Hindia Belanda
merupakan masyarakat yang masih memegang teguh agamanya. Filsafat Francis Bacon misalnya,
kebenaran logika yang dibangun bertujuan untuk menghasilkan prosedur ilmiah yang dapat
diduplikasi tanpa memandang perbedaan konteks . Pengaruh filsafat Bacon pada
bidang hukum kolonial terlihat dari adanya perbedaan perlakuan hukum warga negara di Hindia
Belanda berdasarkan ras. Warga pribumi dan asia lainnya diadili di Landraad dengan hukum lokal,
agama, dan kolonial sebagai salah satu cara mencapai kebenaran logika Barat, sedangkan warga
Eropa diadili di Raad van Justitie hanya dengan hukum kolonial karena dianggap sudah mencapai
kebenaran logika Barat. Praktek pengadilan tersebut semakin parah dengan penunjukan hakim Eropa
saja yang berhak memutuskan karena dianggap merupakan manusia yang logis meskipun kurang
faham konteks sosial yang dibangun dari sistem kepercayaan lokal. Contoh yang lain adalah
bagaimana filsafat politik John Locke diduga tercermin dari praktek penguasaan tanah pertanian dan
perkebunan di Indonesia oleh VOC ataupun Pemerintah Kolonial Belanda melalui praktek TanamPaksa (Cultuurstelsel). Aset-aset penting yaitu tanah dan tenaga kerja dikuasai oleh kaum
aristokratik, kaum buruh bekerja untuk kaum aristokratik dan menggantungkan perekonomiannya
pada kemajuan perekonomian yang didapatkan oleh aristokratik. Pemahaman ini mendorong
penjajah Belanda untuk melakukan kontrak tanah jangka panjang yang tidak seimbang dengan para
raja atau golongan priyayi. Singkat kata Belanda hanya memikirkan hasil bumi dan keuntungannya
dan tidak memperdulikan kondisi tanah dan nasib kaum buruh.
Implikasi Pemikiran Filsafat Terhadap Perkembangan Ilmu Arsitektur Kolonial
Dari pemaparan yang telah dilakukan, Penulis berpendapat bahwasanya cara berfikir
kategorisasi merupakan titik tolak untuk mempelajari ilmu arsitektur kolonial. Hal tersebut karena
situasi arsitektur yang terdapat pada awal masa kolonialisasi di Indonesia yang didominasi 2 kategori
besar yakni arsitektur lokal dan Eropa. Hal ini sesuai dengan kebanyakan penelitian mengenai
arsitektur kolonial Belanda di Indonesia yang menekankan pada aspek karakteristik. Dalam proses
perkembangannya, cara berfikir analogi mulai digunakan untuk menciptakan karya arsitektur yang
lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan arsitektur campuran antara lokal dan Eropa yang
sering disebut sebagai Arsitektur Indis.
Lebih lanjut Arsitektur Indis merupakan bukti bahwasanya cara berfikir manusia menerapkan
pendekatan kategori dan analogi secara beriringan. Dengan mempelajari fenomena arsitektur
kolonial Belanda di Indonesia pada umumnya, dan Arsitektur Indis pada khususnya maka kita
mempelajari bagaimana paradigma arsitektur Barat yang bersumber dari filsafat ilmu pengetahuan
Barat diterapkan di Dunia Timur yang tentunya memiliki konteks sosial dan setting lingkungan yang
sama sekali berbeda.
Mempelajari arsitektur maupun kota kolonial Belanda di Indonesia berarti kita mempelajari
sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Namun demikian tidak menutup kemungkinan
bahwasanya sesuatu yang lampau akan terulang kembali di masa yang akan datang meskipun tidak
persis sama. Singkat kata arsitektur kolonial Belanda di Indonesia menjadi preseden untuk
perkembangan arsitektur Indonesia kedepannya. Hal ini selaras dengan perkembangan pemikiran
manusia yang senantiasa berubah dan berulang antara monisme, dan dualisme.
Secara umum kita mengetahui bahwasanya kolonialisme Belanda di Indonesia dilakukan oleh
dua pelaku yang berbeda yakni VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda. Keduanya tentu memiliki
motif yang berbeda dalam melakukan praktek kolonialisasi di Indonesia, sehingga hal ini tentunya
akan mempengaruhi bentuk arsitektur maupun kota. Kemunculan VOC merupakan bukti dari filsafat
akhir masa kegelapan Eropa yang menginginkan adanya penguatan institusi negara dengan
merangkul kaum pedagang sebagai solusi dari ketidakmampuan gereja dan kerajaan mengayomi dan
mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini selanjutnya menyebabkan sistem monarki absolut
mengalami pembatasan kekuasaan atau bahkan tidak lagi menjadi sistem pemerintahan yang dianut
oleh sebagian besar masyarakat Eropa. Akibatnya muncul beberapa pembaharuan dibidang ideologi,
politik, dan tata pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
warga negara yang mampu berdagang untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan warga
Eropa melalui pajak yang dibayarkan kepada kerajaan. Filsafat Erasmus dan More sebagai salah satu
filsafat yang berpengaruh di Eropa Tengah menghasilkan gagasan untuk melakukan pembagian
peran dalam kenegaraan , Politik, hukum, dan pemerintahan tetap dilakukan oleh
kerajaan dan lembaga-lembaga negara, ekonomi oleh kaum pedagang, dan budaya serta kode
moralitas oleh Gereja . Hal ini dimaksudkan agar tidak terulang kembali tirani seperti
yang terjadi pada zaman kegelapan. Selanjutnya Filsafat Rousseau mengusulkan untuk memberikan
wewenang khusus kepada kaum pedagang atau pemodal untuk mencari sumber daya alam seluasluasnya demi menciptakan kesejahteraan kerajaan dan masyarakat. Filsafat ini juga ditemukan pada
filsafat Leibniz, dan filsafat lainnya yang muncul pada masa renaissance.Didukung oleh semangat kebangkitan dan kemajuan sains dan teknologi dibidang kebumian,
Belanda mengawali penjajahannya dengan motif ekonomi perdagangan di Indonesia. Semula mereka
datang dengan perangai yang merendahkan pribumi sehingga pada ekspedisi yang pertama (1596),
Cornelis de Houtman diusir oleh Kesultanan Banten. Munculnya perangai Belanda yang kurang baik
tampaknya dipengaruhi dari resistensi semangat tumbuhnya modernisme yang mereka bawa dari
Eropa terhadap kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu masih sangat kental dengan unsur-unsur
kosmologi maupun kepercayaan. Lebih khusus, menurut pendapat penulis, pemisahan antara filsafat
dengan teologi serta penolakan terhadap sistem pemerintahan kerajaan yang orang-orang Belanda
bawa dari Eropa kurang sejalan dengan sistem kepercayaan Islam dan sistem pemerintahan
kesultanan di Banten. Hal inilah yang diduga oleh penulis menyebabkan Cornelis de Houtman
beserta rombongan diusir karena memaksakan apa yang mereka yakini. Belajar dari ekspedisi
pertama, pada ekspedisi kedua orang-orang Belanda mampu menahan diri, berpikir lebih
kontekstual, serta bersedia bekerjasama dengan penguasa untuk terlibat pada perang lokal demi
mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Sikap pragmatis menjadikan mereka sukses
pada ekspedisi yang kedua ini.
Selanjutnya Indonesia kemudian banyak menjadi tujuan dari pelayaran Eropa. Tujuannya
sama, yakni berdagang rempah-rempah yang banyak memberikan pemasukan pajak bagi kerajaan
Eropa. Pada tahun 1600an negara-negara Eropa banyak membentuk perserikatan dagang, hal ini
dimaksudkan untuk memperkuat modal semi memenangkan perlombaan dagang. Bahkan, demi
memuluskan keinginan mereka untuk memonopoli perdagangan, mereka rela untuk mengotori
tangannya sendiri menjadi tentara bayaran untuk memihak dan membantu salah satu kerajaan lokal
memerangi kerajaan disekitarnya. Melihat prospek pemasukan pajak yang besar, kerajaan ikut
memberikan dukungan terhadap serikat dagang ini. Adapun serikat dagang yang bersaing ketika itu
antara lain adalah The British East India Company tahun 1600 yang berkedudukan di Kalkutta India,
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1602 yang berkedudukan di Amsterdam dan
Batavia, serta French East India Company tahun 1604 juga berkedudukan di Kalkutta India.
Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwasanya kaum pedagang dan pemodal
mendapatkan peran yang signifikan dan mendapatkan dukungan penuh dari institusi kerajaan di
Eropa. Kebebasan berfikir memberikan kesempatan bagi siapapun yang menguasai ilmu
pengetahuan maupun modal untuk mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya demi
peningkatan kesejahteraan. Mereka berlayar ke luar Benua Eropa berbekal ilmu pelayaran, teknologi
navigasi, dan juga teknologi persenjataan untuk mencari dan mengumpulkan komoditas
perdagangan. Dengan demikian maka pada saat ini orang-orang Belanda tentunya akan lebih
mengutamakan perasaan aman, sembari menunjukkan bahwasanya mereka berada pada posisi yang
lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. bahwasanya benteng merupakan arsitektur kolonial yang mula-mula ada untuk
memfasilitasi keamanan perdagangan. Pada tahap ini arsitektur digunakan sebagai simbol kekuasaan
yang lebih mempertimbangkan aspek keamanan, dan kelancaran aktivitas ekonomi perdagangan.
Tentunya, dikarenakan orang-orang Belanda saat ini belum memiliki hak atas tanah, maka
merekapun belum memungkinkan untuk menerapkan arsitektur maupun penataan kota yang
mempertimbangkan kenyamanan. Benteng-benteng sebagai pos perdagangan sekaligus permukiman menjadi bentuk sederhana
dari kota yang didirikan di daerah aman yakni di wilayah pelabuhan ataupun muara sungai
. Barulah di pertengahan kedua abad ke-17 dan 18 setelah orang-orang Belanda
memiliki hak atas beberapa wilayah tanah yang didapatkan dari keikutsertaan mereka pada
peperangan antar kerajaan lokal, mereka mulai berfikir dan bertindak untuk lebih menguasai
komoditas perdagangan yang mereka monopoli dari sektor hulu ke hilir . Oleh
karena itu maka diberlakukanlah politik tanam paksa (cultuurstelsel) yang kemudian menarik minat
penduduk Eropa yang lebih banyak untuk datang menguasai sektor pertanian maupun perkebunan
yang menghasilkan komoditas favorit di Pasar Eropa. Selanjutnya hal ini kemudian memicu
munculnya pemukiman-pemukiman Belanda di Indonesia khususnya berada di daerah pesisir
Abad ke 19 merupakan abad yang cukup bersejarah bagi Indonesia. Pada abad ini modernisasi
yang tumbuh pesat di Eropa mulai masuk dan berkembang di Indonesia seiring dengan pemberlakukan beberapa kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai pelaku baru kolonialisme
di Indonesia. Kebijakan-kebeijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan Politik Etis, Liberalisasi
Agraria, serta Pemerintahan Desentralisasi. Adapun pelaku dari modernisasi di Indonesia adalah
orang-orang Eropa asli maupun orang-orang Indonesia yang berhasil menyelesaikan studinya di
Eropa dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Pelaku modernisme tersebut diduga mencoba
mengedepankan nilai-nilai kebebasan berfikir manusia melalui penciptaan gaya hidup di Indonesia
yang lebih menonjolkan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi permasalahan
masyarakat. Derasnya arus ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ditambah tekanan
pengawasan penerapan Politik Etis dari masyarakat Eropa terhadap Indonesia mengakibatkan sekatsekat sosial di Hindia Belanda terbuka meskipun tidak sempurna. Hal ini dikarenakan konstruksi
berfikir manusia yang pada saat itu mempercayai bahwasanya ilmu pengetahuan merupakan sesuatu
yang sifatnya universal dan dapat diterapkan dimanapun, maka setiap warga yang mampu berhak
menerima ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya. Dari fenomena diatas kita
dapat menarik kesimpulan bahwa pemikiran monoisme dalam arti hanya mengakui satu golongan
masyarakat yaitu masyarakat berilmu yang saat itu didominasi oleh orang-orang Belanda dan kaum
bangsawan muncul masa ini.
Penerapan Politik Etis menurut penulis merupakan salah satu contoh dari wujud pemikiran
monisme di bidang politik pemerintahan tanah jajahan, politik tersebut berkeinginan untuk
menyetarakan kedudukan pribumi dengan orang Eropa menggantikan sistem kasta yang sebelumnya
diterapkan. Alhasil, politik ini mampu mendorong gerakan diberbagai bidang yang berorientasi
mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Salah satu contoh dari gerakan tersebut adalah
munculnya partai politik Indische Partij yang oleh para ahli sejarah diyakini sebagai tonggak awal
modernisme dalam segi pemikiran politik bagi warga pribumi pada masa kolonialisasi Belanda.
Pada abad ke-19 ini, arsitektur dan perencanaan kota kolonial Belanda di Indonesia dihadapkan
kepada tantangan untuk memenuhi tingginya angka kebutuhan permukiman bagi orang-orang Eropa
yang salah satu sebab utamanya adalah kemudahan migrasi lintas benua akibat dibukanya Terusan
Suez yang menjadikan jarak tempuh dari Benua Eropa menuju Asia lebih dekat. Akibatnya banyak
orang Eropa mencoba peruntungan ekonomi di Benua Asia seperti yang pernah dilakukan oleh
orang-orang Eropa sebelumnya. Di sisi lain arus urbanisasi di Indonesiapun semakin tinggi akibat
adanya jalan pos besar (De Grote Postweg) dan pembukaan jalur-jalur kereta api yang mampu
menghubungkan kota-kota di pesisir dengan pedalaman pulau
Pemerintah Kolonial Belanda kemudian menerapkan kebijakan pembangunan pemukiman
berbasis standarisasi desain rumah sehat dan industrialisasi bahan bangunan sebagai salah satu
solusinya. Burgerlijke Openbare Werken atau Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Kolonial
Belanda menjadi ujung tombak dari penerapan kebijakan pembangunan tersebut dengan
mengeluarkan perencanaan kota, panduan desain untuk rumah sehat, dan pengawasan penggunaan
bahan bangunan. Standarisasi, dan industrialisasi kemudian digunakan sebagai paradigma arsitektur
untuk menyelesaikan permasalahan permukiman dengan cepat . Namun demikian
tampaknya industrialisasi dan standarisasi juga memiliki beberapa efek samping. Yang pertama
adalah berkurangnya eksplorasi dibidang arsitektur akibat penyederhanaan rasa atau persepsi
manusia terhadap sesuatu. Manusia kemudian semakin fokus pada hal-hal yang terukur saja. Hal-hal
yang sifatnya tidak terukur seperti nilai simbolisme semakin berkurang. Permasalahan baru yang
kedua adalah eksploitasi alam yang berlebihan. Meskipun demikian, penulis berpendapat
bahwasanya standarisasi juga membawa dampak positif yakni semakin terukurnya kenyamanan
arsitektur kolonial Belanda di Indonesia meskipun belum secara kuantitatif.
Fenomena yang dijabarkan pada paragraf di atas tampaknya sesuai dengan pernyataan
beberapa filsuf penting di abad ke 18. bahwa ide (pokok pikiran
manusia) berasal dari indera serta persepsi, karena ide bersifat terukur dan dapat diindera maka ide selanjutnya mungkin diterapkan pada hal lain selama permasalahan yang dihadapi sama tertulis pada buku The
Dialogues of Hylas and Philonous. Berkeley menyatakan bahwa sebuah realitas adalah fenomena
mental, respon indera atas suatu realitas tidak akan mampu membuat kesimpulan atas suatu sifat
benda, melainkan sifat tersebut tergantung pada persepsi orang yang melihatnya ,
Dari dua buah karya filsafat diatas kita dapat memperoleh gambaran bahwasanya keberhasilan dari
suatu ilmu pada masa ini semata-mata hanya dilihat dari apakah ilmu tersebut mampu memenuhi
tujuannya secara terukur. Jika dihubungkan dengan arsitektur maka tujuan yang dapat diukur secara
obyektif adalah fungsi yang selanjutnya diidentikkan dengan ruang.
Dengan demikian maka elemen bentuk pada arsitektur mengalami degradasi makna oleh
manusia. Bentuk arsitektur yang dahulu dianggap sebagai salah satu elemen yang dapat membedakan
(identitas) karya arsitektur yang satu dengan yang lain tidak lagi dipandang menjadi bagian penting.
Manusiapun kemudian merasa tidak perlu untuk menerapkan simbolisme dalam arsitektur sebagai
bahasa identitas. Dengan demikian maka bentuk bangunan dipandang hanya sebagai penutup yang
berfungsi melindungi bagian dalam bangunan. Kondisi ini tercermin dari persepsi masyarakat
kolonial pada abad ke 19 dan 20 mengenai karya arsitektur dimana arsitektur yang baik adalah
arsitektur yang fungsional. Untuk menunjang arsitektur yang lebih mengutamakan fungsi maka
penyelesaian bagian luar (enclosure) bangunan didesain bebas dari ornamen yang diidentikkan
dengan upaya menghadirkan simbol dalam arsitektur.
Menguatnya keinginan untuk lebih menyelesaikan fungsi dan mengurangi simbolisme pada
bentuk juga dapat dilihat dari morfologi desain arsitektur permukiman dan perumahan kolonial yang
semakin sederhana. Namun demikian faktor kesehatan tidak dapat diabaikan oleh manusia agar dapat
menikmati fungsi dalam arsitektur. Orang-orang Belanda secara sadar menyadari bahwa mereka
harus beradaptasi dengan perbedaan iklim dan lingkungan yang ada. Hal ini kemudian menjadikan
penerapan modernisme pada arsitektur kolonial Belanda di Indonesia tidak mutlak berdasarkan
pemikiran monoisme (standarisasi dan industrialisasi) melainkan beralih ke dualisme. Orang-orang
Belanda tersebut merasa perlu menerapkan elemen-elemen eksterior bangunan yang dapat
menciptakan kenyamanan fungsi di bagian dalam bangunan melalui pengamatan empiris. Hal ini
menurut pemikiran penulis merupakan wujud dari pendekatan berfikir analogi dari tubuh manusia,
dimana kulit yang sehat merupakan salah satu tanda tubuh yang sehat. Selanjutnya melalui
pengamatan empiris diketahui bahwasanya elemen-elemen eksterior bangunan lokal merupakan
contoh terbaik yang ada ketika itu.
Penulis berpendapat bahwasanya munculnya arsitektur indis yang merupakan campuran antara
arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal adalah wujud pemikiran dualisme yang pada akhirnya
menjadi ciri pembeda dengan arsitektur modern Eropa yang menjadi acuan awal. Adapun
karakteristik utama bangunan Indis , perpaduan
bentuk antara arsitektur Barat dengan arsitektur lokal melalui penggunaan atau re-desain elemenelemen eksterior bangunan lokal sebagai penyelesaian selubung bangunan (building envelope).
Arsitektur Indis pada masa kolonialisasi Belanda memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat
. Bangunan arsitektur indis mampu tampil sebagai bangunan yang fungsional,
mejadi simbol dari bangsa Eropa yang saat itu dianggap sebagai penguasa, berestetika baik, serta
nyaman ditinggali karena mampu beradaptasi dengan lingkungan dan iklim setempat. Pada akhirnya
dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh perkembangan filsafat ilmu pada bidang arsitektur kolonial
melahirkan kesadaran berfikir bahwasanya manusia perlu kembali menjadikan alam sebagai sumber
berfikir dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Adapun identitas yang
dituangkan dalam praktek simbolisme perlu diterapkan dengan mengedepankan keselarasan dengan
alam agar manusia tetap dapat hidup dan berkehidupan dalam ruang lingkup arsitektur dan
perencanaan kotamakna atau ide dasar dari suatu fenomena yang diceritakan kembali secara sistematis dan
komprehensif melalui berbagai sudut pandang. Dengan adanya metodologi-metodologi penelitian
tersebut maka penelitian sejarah ataupun penelitian yang menggunakan objek sejarah semakin
mengarah ke hal-hal yang sifatnya tematik. Namun demikian pada kajian arsitektur kolonial Belanda
di Indonesia tidak memungkinkan untuk menerapkan metodologi penelitian fenomenologi. Hal ini
dikarenakan peneliti tidak lagi bisa merasakan dan bersinggungan secara langsung dengan
kebudayaan atau kehidupan sehari-hari dari orang-orang Belanda di Indonesia. Selanjutnya, tradisitradisi ini dapat menggunakan beragam metode penelitian sesuai dengan fokus ataupun keluaran
penelitian yang diharapkan. Selanjutnya akan dibahas kemungkinan penggunaan ragam metode
penelitian untuk bidang arsitektur kolonial Belanda di Indonesia pada paragraf di bawah ini.
Mengacu pada sub bab sebelumnya, bahwa perkembangan pemikiran arsitektur kolonial di
Indonesia berawal dari masa VOC yang dimulai dari keinginan untuk menonjolkan identitas guna
mendapatkan pengakuan atau kedudukan yang lebih tinggi yang kemungkinan berimplikasi pada
meningkatnya rasa aman bagi orang-orang Belanda. Dengan paradigma monisme yang mereka pakai
dimana mereka hanya mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya bentuk arsitektur yang baik
adalah arsitektur Eropa, mereka menandai dan menciptakan teritori sebagai penegasan kategori yang
berbeda antara orang Belanda yang dianggap beradab, dengan orang lokal yang dianggap kurang
beradab. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat menggunakan beberapa metode seperti kajian
literatur, komparasi kasus antar sesama kasus arsitektur kolonial, dan metode penelitian lainnya.
Selanjutnya seiring dengan semakin berkuasanya orang-orang Belanda di Indonesia di akhir
masa pemerintahan VOC, mereka semakin dapat mengontrol sendi-sendi kehidupan di Indonesia.
Pada saat ini dasar pemikiran yang digunakan tetap monisme meskipun arsitektur Eropa yang
diterapkan semakin memiliki tipologi yang beragam. Adapun yang berkembang adalah bangunanbangunan tersebut membentuk suatu sistem yang terpisah dengan sistem lokal yang telah ada
sebelumnya. Sistem tersebut dapat berbentuk permukiman, ataupun kota kolonial. Oleh karena itu
arsitektur kolonial Belanda pada masa ini dapat dikatakan sebagai simbol kekuasaan atas orangorang lokal. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat menggunakan beberapa metode seperti
kajian literatur, komparasi kasus antar sesama kasus arsitektur kolonial atau antar kasus arsitektur
lokal dan kolonial, etnografi yang menyinggung mengenai simbol-simbol dari kebudayaan, tipomorfologi dan metode penelitian lainnya.
Memasuki abad ke 19, seiring dengan perpindahan kekuasaan kolonial Belanda dari VOC
kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan munculnya paham moderisme di Eropa, monisme
yang menjadi latar belakang pemikiran dari arsitektur kolonial Belanda di Indonesia berubah wujud
seiring dengan masuknya paham modernisme di Indonesia. Fungsionalisme dan industrialisme
dianggap menjadi solusi utama pemecahan masalah arsitektur dan perencanaan kota saat itu. Hal ini
dikarenakan saat itu manusia memerlukan kecepatan untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan
dua hal di atas merupakan reduksi atas kompleksitas solusi yang mungkin bisa diambil. Keadaan ini
terus berlangsung setidaknya sampai dengan akhir abad ke 19. Monisme pemikiran yang terjadi pada
masa ini dalam konteks arsitektur kolonial Belanda cenderung menjadikan manusia menjauhi alam,
manusia di Indonesia mulai meninggalkan alam sebagai sumber pembelajaran sehingga arsitektur
yang dihasilkan terkesan kurang ramah terhadap alam. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat
menggunakan beberapa metode seperti kajian literatur, komparasi kasus, etnografi, tipo-morfologi
dan metode penelitian lainnya.
Cara berfikir dualisme mulai mengikis cara berfikir monisme pada akhir abad ke 19 hingga
berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun demikian tampaknya sampai akhir
penjajahan Belanda di Indonesia, cara berfikir dualisme tidak menggantikan cara berfikir monisme
dalam konteks arsitektur dan perencanaan kota kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa ini, arsitek
dan perencana kota mulai kembali melihat alam sebagai sumber pembelajaran serta memaknai
arsitektur lokal yang sebelum kehadiran arsitektur Eropa di Indonesia telah ada sebagai buah pemikiran arsitektur yang berhasi mengatasi tantangan iklim dan lingkungan tropis. Di bidang
arsitektur, munculnya arsitektur indis dapat dianggap sebagai tesis atas permasalahan kesehatan dan
kenyamanan arsitektur yang dicari oleh arsitek saat itu. Di bidang perencanaan kota, adaptasi
penggunaan prinsip garden city pada perencanaan kota-kota kolonial di Indonesia dianggap sebagai
solusi atas keinginan manusia mendapatkan kualitas lingkungan yang lebih baik atas kota tempat ia
tinggal. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat menggunakan beberapa metode seperti kajian
literatur, komparasi kasus antar sesama kasus arsitektur kolonial atau antar kasus arsitektur lokal dan
kolonial, tipo-morfologi dan metode penelitian lainnya khususnya yang mengenai kinerja bangunan.
di Indonesia Terhadap Alam dan Manusia
Dengan memperhatikan perkembangan keilmuan arsitektur pada umumnya, dan perkembangan
keilmuan arsitektur kolonial khususnya maka kita mendapatkan gambaran bahwasanya arsitektur
tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya manusia dan setting lingkungan yang ada.
Fenomena arsitektur kolonial Belanda di Indonesia memberikan gambaran bahwasanya pemikiran
filsafat barat juga mempengaruhi dunia timur. Dinamisme cara berpikir monisme dan dualisme
dengan alam dan manusia sebagai titik tolaknya, melahirkan cara pandang baru yang lebih ilmiah
terhadap perkembangan arsitektur di Indonesia pada saat itu.
Cara berfikir yang bertitik tolak pada manusia (anthroposentris) merupakan dasar pemikiran
arsitektur maupun perencanaan kota yang pertama kali diterapkan. Keinginan untuk menonjolkan
teritori dan identitas sebagai pembeda antara Belanda dengan masyarakat lokal diduga menjadi latar
belakang utama bagaimana arsitektur Eropa yang diterapkan di Indonesia pada awal kedatangan
VOC hingga akhir abad ke 18 tidak mempertimbangkan kesesuaiannya dengan konteks sosial
maupun setting lingkungan yang ada. Dari uraian di atas jelaslah bahwa berfikir kategorisasi
merupakan model berfikir arsitektur kolonial yang paling awal.
Memasuki abad 19 hingga pertengahan menjelang akhir abad ke 19, pengaruh modernisme di
Eropa menjadikan cara berfikir arsitektur maupun perencanaan kota kolonial di Indonesia semakin
kental dengan nuansa monisme. Cara berfikir ala mesin yang menganut nilai kebenaran tunggal
menjadi semangat untuk menyelesaikan pertumbuhan angka permukiman dan kota yang semakin
cepat.
Barulah kemudian memasuki abad ke 20, cara berfikir manusia mulai diwarnai oleh alam. Hal
ini dikarenakan masyarakat kolonial ketika itu mulai sadar bahwa wujud arsitektur maupun kota
yang ada membawa efek negatif bagi mereka karena pembangunannya yang tidak selaras dengan
karakteristik iklim dan lingkungan setempat. Selanjutnya fenomena ini mengantarkan pada
munculnya dualisme dalam memikirkan arsitektur dan perencanaan kota yang paling baik di
Indonesia menurut orang-orang Belanda. Pada masa ini orang-orang Belanda mulai menggali
pengetahuan arsitektur lokal yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Dari sinilah kemudian model
berfikir arsitektur maupun perencanaan kota kolonial di Indonesia mulai menggunakan model
analogi. Hal tersebut dapat terlihat dari praktek-praktek desain yang dilakukan oleh orang-orang
Belanda dimana mulai memasukkan unsur arsitektur lokal ke dalam wujud arsitektur Eropa, ataupun
mulai mensintesakan antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal meskipun terkadang hanya pada
taraf elementer saja. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan wujud arsitektur yang kontekstual
terhadap konteks sosial maupun setting lingkungan. Singkat kata, pada akhirnya pengetahuan
mengenai arsitektur kolonial di Indonesia membawa kita kembali kepada cara berfikir yang
bersumber pada alam dengan nilai kebenaran yang relatif (tidak mutlak) sesuai dengan konteks yang
ada. Bahwa manusia merupakan bagian kecil dari alam, dan tidak dapat menentang alam kecuali
untuk kehancuranya sendiri.
Pada bulan Desember 1903, seorang pelancong dari Samarinda tiba di Pelabuhan
Surabaya. Dalam perjalanan dari pelabuhan menuju ke penginapan maupun saat
berkeliling kota di hari berikutnya, hanya kekaguman yang dirasakannya. Berbagai
aktivitas masyarakat dan fasilitas pendukung kota, seperti perkampungan padat, perumahan eksklusif orang kulit putih, deretan pertokoan, jalan raya, lorong (gang),
dan hilir mudik kendaraan, belum pernah dijumpai di kota lain. Sebagai ungkapan
ekspresi kagum pada kota ini, dia menyatakan “djika orang-orang koerang pande
berdjalan-djalan di kota ini ta’bolih tida temtoelah sesat badannja ta’tahoe
menoedjoe, [.....]” (BS 17/2/1904). Kesaksian ini menginformasikan dan menegaskan
bahwa Surabaya telah berubah dari kota tradisional menjadi kota modern pada awal
abad ke-20.
Perubahan kota tentu tidak terjadi secara mendadak, tetapi berlangsung melalui
proses panjang pengaruh industrialisasi sejak pertengahan abad ke-19. Menurut H.
W. Dick (2000:177; 2002:253), kegiatan ekonomi industri inilah yang menyebabkan
Surabaya berubah status menjadi kota industri dari agraris. Perubahan kota juga
didukung oleh kemajemukan kegiatan ekonomi produksi (pertanian dan
perkebunan) dan distribusi (pertokoan, pergudangan, dan pasar). Sektor pertanian
dan perkebunan merupakan pendukung utama perdagangan pada pertengahan
abad ke-19, tetapi sejak akhir abad ke-19 produk industri ikut berkontribusi
menyuplai kebutuhan perdagangan. Ini ditandai oleh munculnya beberapa jenis
pabrik, antara lain perkapalan, peleburan tembaga, sabun, minuman, makanan, dan
peralatan rumah tangga.
Perwujudan kemajuan dan modernitas kota juga ditunjukkan oleh perkembangan
infrastruktur, seperti jalan, rel, pelabuhan, dan bangunan. Pembangunan
infrastruktur membuktikan penerimaan masuknya alat transportasi baru, seperti
kereta api, trem, truk, bus, mobil, dan sepeda motor. Industri dan transportasi
ternyata mendorong laju migrasi yang berimplikasi pada pertambahan jumlah
penduduk kota dari tahun ke tahun dan perubahan komposisi penduduk.
Akibatnya, perluasan permukiman penduduk tidak dapat dihindari sebagai efek
kecenderungan positif perekonomian. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini
membahas perubahan Surabaya menjadi kota modern yang ditandai oleh
industrialisasi, transportasi, dan permukiman, dalam kisaran waktu akhir abad ke-
19. Perubahan kota berpengaruh pada komposisi penduduk dan kehidupan
masyarakat.
Secara teoretis, perkembangan kota modern berhubungan dengan berdirinya
berbagai jenis industri sebagai tempat penduduk kota bekerja (Ginsburg 1989:78).
Perkembangan industri merupakan tahapan tipe kota setelah agraris dan praindustri (Nas 1986a:5). Surabaya disebut kota agraris ketika dikendalikan oleh
otoritas lokal yang berlangsung pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18.
Hal ini berarti kelahiran kota tidak secara spontan atas kehendak pedagang,
pengrajin, dan petani, tetapi tergantung pada otoritas raja sehingga juga disebut
kota tradisional. Kompleks abdi dalem dan pemerintahan didesain mengelilingi
kraton, kemudian berkembang menjadi perkampungan, seperti Kampung
Kranggan, Maspati, Tumenggungan, Carikan, dan Kepatihan. Perkembangan
kampung lainnya disusun berdasarkan istilah pertanian, pertukangan,
perdagangan, dan pasar, yang menunjukkan karakteristik perekonomian kota tradisional ditopang oleh kegiatan pertanian, kerajinan, dan perdagangan (Lombard
2000:218).
Kota Surabaya di bawah kendali bangsa asing dimulai ketika VOC berkuasa pada
tahun 1743. Sejak saat itu, VOC lebih leluasa mendirikan kota sesuai model dan ciriciri kota di Eropa, seperti tembok kota, kanal, dan benteng. Pusat kota bergeser dari
tempat kedudukan raja (negaragung) ke kompleks perdagangan dan permukiman
Belanda. Meskipun pusat kota dan kegiatan komersial telah dikendalikan oleh VOC,
karakteristik aktivitas ekonomi masih serupa dengan periode sebelumnya, yaitu
pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Transisi Surabaya menjadi kota praindustri
dimulai pada awal abad ke-19. Kampung dan permukiman kota belum menjadi
bagian persoalan kota yang serius karena lahan-lahan masih tersedia luas untuk
pembangunan permukiman baru, tetapi kota mulai menghadapi persoalan terkait
kepadatan kampung yang semakin meningkat yang berakibat pada memburuknya
keadaan fisik kampung. Pada dekade ketiga abad ke-20, pemerintah
mengagendakan program khusus perbaikan kampung (Kampong Verbetering).
Pada era setelah kemerdekaan juga muncul KIP (Kampung Improvement Program).
Ketika waktu semakin bergerak jauh dari titik awal Surabaya sebagai kota modern,
masalah yang dihadapi semakin rumit terutama permukiman liar di bantaran
Sungai Mas yang menjadi ikon kota (King dan Idawati 2010). Hal ini berarti
perubahan kota membawa konsekuensi pada persoalan lain. Tulisan ini tidak akan
menjelaskan akibat perubahan kota, tetapi penekanan tertuju pada realitas objektif
tentang Surabaya pada akhir abad ke-19.
Surabaya sebagai kota praindustri bertepatan dengan masa F.J. Rothenbuhler (1799-
1808) menjabat gezaghebber ujung timur Jawa. Pada saat itu, infrastruktur pertahanan
kota berupa pabrik senjata dan peralatan perang (constructie winkel) mulai dibangun
di Kalisosok. Pabrik senjata merupakan awal kemunculan industri skala besar yang
berpengaruh pada terciptanya peluang kerja dalam bidang pengecoran tembagakuningan-besi, perakitan senjata, dan pembukuan (von Faber 1931:127). Kebijakan
Sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Joannes van den Bosch (1830-1833)
tidak hanya meningkatkan volume perdagangan yang dikuasai oleh Nederlandsche
Handel Maatschapij (disebut Koempeni Ketjil) pada pertengahan abad ke-19 (PP
24/3/1924), tetapi juga menyebabkan industri semakin berkembang khususnya
industri gula.
Kebijakan Tanam Paksa mengubah wilayah pinggiran kota sebelah selatan sampai
kawasan Sidoarjo menjadi sentra perkebunan tebu. Perkebunan tebu pertama di
Jawa Timur terdapat di Pasuruan yang ditanami sejak akhir abad ke-18 sebagai
pengembangan dari Batavia, kemudian diikuti oleh berdirinya pabrik gula juga di
Pasuruan pada 1779 oleh Han Kit Ko. Industri gula di Surabaya berkembang pesat
pada tahun 1830-an (Lombard 2000:248, 463). Beberapa pabrik gula di sekitar
Surabaya adalah Buduran, Waru, Karang Bong, dan Ketegan pada tahun 1835;
Candi pada tahun 1837; Watutulis, Balongbendo, Gedek, dan Seranten pada tahun
1839; dan Sruni pada tahun 1940. Pabrik gula yang terdapat di kawasan Surabaya di
antaranya Ketabang, Jagir, Karah, Darmo, Keputran, Gubeng, Bagong, Dadongan,
dan Petemon. Beberapa pengusaha pabrik gula di Surabaya dan sekitarnya antara
lain J.E. Banck, von Franquemont, J.D. Kruseman, The Goan Tzing, Han Kok Tie,
Notto Dipuro, dan Soemo Diwirjo (von Faber 1931:178-179; Tjiptoatmodjo 1983:132).
Kemunculan pabrik gula di beberapa tempat tentu menciptakan kesempatan kerja
baru, baik di bidang produksi maupun di gudang-gudang penyimpanan gula.
Produksi gula dengan tenaga binatang mulai diganti dengan peralatan modern
(mesin uap) pada tahun 1830-an, sehingga mengubah volume dan percepatan
produksi gula. Sejak saat itu, penggunaan teknologi uap mendorong kemunculan
usaha lain, yaitu penyediaan alat angkut dan perawatan mesin. Alat angkut gula
menggunakan pedati (cikar) dari pabrik ke gudang dianggap kurang efisien. Hal ini
mendorong Firma Besier en Jonkheym mulai menjual lokomobil (locomobiel) pada
tahun 1868 sebagai alat angkut gula (von Faber 1931:180). Perubahan alat produksi
juga melahirkan pengusaha bengkel reparasi dan pembuatan ketel. Industri yang
dibangun tidak hanya terbatas pada perangkat produksi gula, tetapi juga terus berkembangnya industri lain, seperti peralatan uap, kapal, senjata, pengecoran besi
dan tembaga, dan kerajinan (Dick 2000:253-258).
Perkembangan industri pada masa Sistem Tanam Paksa ditandai oleh lahirnya
pengusaha. Pengusaha perintis yang bergerak di bidang peralatan berat adalah
Frans Jacob Hubert Bayer. Keahliannya tidak dihabiskan sebagai pekerja biasa di
bengkel konstruksi pemerintah, tetapi beralih profesi menjadi pengusaha petualang.
Hal ini ditunjukkan ketika F.J.H. Bayer mengundurkan diri dari pekerjaan pada
tahun 1841, kemudian mendirikan pabrik peralatan uap De Phoenix yang
berkembang baik dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 1844, pabrik ini dijual kepada
pemerintah dan hasil penjualan digunakan lagi sebagai modal mendirikan pabrik
De Volharding yang dikelola hinggadia meninggal pada tahun 1879 dalam usia 72
tahun (BT 15/1/1879).
Beberapa tokoh industrialis lain adalah Bezier en Jonkheym, C.F. Huysdens, dan F.
Willems. Industri permesinan didirikan oleh Bezier Jonkheym en Smith di Kalimas,
C.F. Huysdens di Rustenburgerpad, dan F. Willems di Grisseescheweg. Industri
tempat tidur dari besi (ijzeren ledikanten) terdapat di beberapa tempat, seperti di
Chineesche Voorstraat (dikelola oleh A. Matzen), Boomstraat (Meduwe Schmid),
dan Kalimas (Haije dan van Marle). Industri konsumsi sehari-hari juga berkembang,
misalnya pabrik sabun di Kalongan didirikan oleh Rosemier en Perret, dua pabrik es
di Societeitstraat dikelola oleh G. Kuneman dan J.J. Spiekerman, dan pabrik air
minum (waterfabriek) milik J.A.A. Nicolai terdapat di Kalimas (Anonim 1872: 39).
Sebagian besar industri yang berkembang pada pertengahan abad ke-19 ternyata
didominasi oleh pembuatan barang kerajinan tangan. Industri kerajinan
mengandalkan bahan dari kayu, kulit, dan logam. Produk yang dihasilkan berupa
barang jadi dan setengah jadi untuk memasok instrumen kapal, kereta kuda, mebel,
dan rumah. Adres-boek 1872 menyebutkan bahwa kampung-kampung di Kota
Surabaya identik dengan pekerjaan kerajinan, seperti arloji di Kampung Pecantian,
pengecoran tembaga dan kuningan di Kampung Kawatan dan Pabean, pengolahan
kulit di Kampung Songoyudan, pembuatan kereta kuda di Kampung Donorejo,
pelana di Kampung Kramatgantung, dan tambangan di Kampung Bandaran
(Anonim 1872:40). Perekonomian kampung yang bersumber dari sektor kerajinan
semakin menguat sehingga beberapa kampung dikenal sebagai kampung pengrajin,
seperti Kampung Pecantikan (kampung reparasi atau pengrajin jam tangan),
Pesapen (meubelmakers, pengrajin meubel), Kawatan (kopergieters, pengrajin
tembaga), Pabean (geelgieters, pengrajin dari kuningan), Bubutan dan Maspati
(draaijers, ivoor, en hoornwerkers, tukang bubut, gading, dan tanduk), Kampung Baru
(bathikers, pengrajin batik), Ampel (kledermakers, penjahit pakaian), dan Sangayudan
(huidenbereiders, pengrajin kulit) (Anonim 1872:53). Beberapa jenis industri kerajinan
melahirkan tenaga terampil yang disebut tukang.
Jumlah pekerja di bidang pertukangan sebanyak 13.347 orang, seperti tukang kayu,
perabot rumah tangga, batik, kapal, kereta, dan pengecoran kuningan, tembaga, dan
besi (von Faber 1931:183-184). Golongan Bumiputra mengisi semua jenis pekerjaan, kecuali pengrajin besi (bukan pande besi) dan pembuat roti. Persentasi pekerja dapat
dihitung melalui jumlah penduduk kota pada 1859, yaitu 34.927 jiwa (2.404 Eropa,
1.809 Cina, Arab, India, dan golongan lain, 30.714 Bumiputra). Jumlah golongan
Eropa yang bekerja di sektor industri pertukangan sebesar 289 orang sama dengan
12%, sedangkan golongan Cina, Arab, dan India, dan golongan lain sebesar 952
sama dengan 52%. Golongan Eropa yang dianggap sebagai tuan ternyata memiliki
kelompok yang berprofesi dalam bidang pertukangan.
Pertumbuhan jenis pekerjaan di sektor industri secara bertahap mengubah pola
kerja. Jika pekerjaan di sektor pertanian didasarkan pada ikatan tradisional selama
kurun waktu sebelum abad ke-19, kemunculan industri mengubah ikatan yang
diatur oleh pengusaha (Burger 1983:14). Pada awal abad ke-20, perkembangan lebih
lanjut sektor industri melibatkan penanam modal dari Eropa yang bergerak dalam
skala besar di berbagai bidang, misalnya industri logam, es, mineral, kilang minyak
dan gas, galangan kapal, dan percetakan (Dick 2002:262-267). Kawasan industri yang
dikembangkan bergeser ke selatan kota di daerah sekitar Ngagel sebagai bukti
bahwa industrialisasi pada awal abad ke-20 bergerak dinamis.
Infrastruktur dan Transportasi
Perkembangan industri seperti dijelaskan di atas didukung oleh beberapa faktor,
seperti pemerintah kolonial, teknologi, inovasi, bahan baku, tenaga kerja, dan
modal, terbukti mengantarkan Surabaya bergerak dinamis. Faktor pendukung lain
adalah percepatan distribusi yang berhubungan dengan perbaikan, pelebaran, dan
pembuatan jalan baru, misalnya jalan lebar dibuka antara Keputran dan Kayun.
Perbaikan jalan diawali pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811)
membuka jalur pos yang melintas Kota Surabaya. Jalan utama kota mendapatkan
perhatian serius pada paruh kedua abad ke-19 ketika aspal sebagai material penting
pengeras jalan. Ini berarti infrastruktur jalan merupakan sarana utama percepatan
distribusi. Distribusi barang dan angkutan orang sebelum muncul kendaraan mesin
masih mengandalkan alat transportasi tradisional, seperti pedati (cikar) dan kereta
kuda.
Kereta kuda digunakan sebagai alat transportasi ke tempat bekerja. Bagi pekerja
berpenghasilan rendah, menyewa kereta kuda memberatkan jika hanya untuk
keperluan berangkat kerja. Realitas ini menginspirasi A. Ledeboer membuka usaha
angkutan umum pada tahun 1859 yang tarifnya tentu lebih murah. Kereta kuda
berangkat pada pagi hari menuju ke pusat kegiatan ekonomi, kemudian
mengantarkan para pekerja kembali pulang pada sore hari. Kereta kuda sederhana
dan murah disebut dos-a-dos (dilafalkan menjadi sado), yakni kereta kecil roda dua
dengan tempat duduk penumpang saling membelakangi. Setelah dilakukan
modifikasi, kendaraan ini juga disebut dokar pada tahun 1877. Muncul lagi istilah
kosong untuk menyebut dokar ketika calon penumpang mencegat dokar sewaan di
jalan (von Faber 1931:197-198). Sebutan kosong merupakan bentuk pertanyaan pada
kusir dokar sewa yang kembali ke rumah dalam keadaan kosong setelah
mengantarkan penumpang atas perintah majikan. Usaha kusir memperoleh pendapatan tambahan dilakukan dengan cara mengangkut penumpang dan
mengantarkan ke alamat yang dituju dengan pembayaran langsung ke kusir.
Pedati dan kereta kuda mendapatkan saingan ketika hadir alat transportasi baru,
yaitu kereta api dan trem uap. Rel dibangun secara bertahap pada akhir abad ke-19.
Pembangunan rel Surabaya-Pasuruan dan Surabaya-Malang (disambungkan di
Bangil) dilakukan oleh Perusahaan Kereta Api Negara (Staatspoorwegen), yang
dimulai pada 1875, merupakan keputusan parlemen dan pemerintah Belanda (BT
18/5/1878). Ini terjadi setelah satu dekade pembukaan jalur kereta api antara
Semarang dan wilayah-wilayah kerajaan di Jawa Tengah (Knaap 1989:12). Pada
tahun 1878, jalan besi pertama di Jawa Timur selesai dikerjakan. Sehubungan
dengan hal ini, Gubernur Jenderal Johan Willem van Landberge (1875-1881) datang
ke Surabaya, seperti diabadikan dalam syair yang dimuat di Bintang Timor
(18/5/1878).
Soenggoeh rameh di Surabaija,
Datengnja goebernoer dengen bininja,
Goebernoer VAN LANSBERGHE itoe namanja,
Kaja dan meskin kloewar semoeanja,
Kapal belaboe berboeni meriam,
Tinggal kwali di atas keren,
Denger djindral njang soeda dateng
Masak nasi setengah mateng
Kedatangan gubernur jenderal meresmikan jalur pertama kereta api SurabayaPasuruan dan pembukaan pameran pertanian. Pejabat yang memberi sambutan
dalam peresmian adalah Gubernur Jenderal Johan Willem van Landberge, Inspektur
Jenderal Kolonel David Maarschalk, dan pejabat kepala pembangunan jalur rel, H.G.
Derx. Setelah acara seremonial, gubernur jenderal beserta pejabat yang hadir
mengawali perjalanan kereta api dari Surabaya menuju Pasuruan pada tanggal 16
Mei 1878 (BT 18/5/1878). Perjalanan ini merupakan momentum penting yang
memberi makna bahwa kereta api sebagai angkutan penumpang jarak jauh dan
distribusi hasil perkebunan. Komoditas pertanian dan perkebunan dari pedalaman
terdistribusikan dengan baik, sehingga mendukung Kota Surabaya semakin kuat
sebagai pusat perdagangan ekspor-impor. Jadwal keberangkat dari Kota Surabaya
menuju Pasuruan dalam satu hari, yaitu pada pukul 07.00 dan 14.30, sedangkan
keberangkatan sebaliknya pada pukul 06.15 dan 14.10. Jadwal perjalanan kereta api
menambah pengalaman hidup baru penumpang terkait kedisiplinan terhadap
waktu (von Faber 1931:201). Jalur kereta api disambungkan ke kota-kota lain di
bagian selatan dan timur. Gubernur Jenderal Johan Willem van Landberge datang
lagi ke Kota Surabaya meresmikan jalur rel kereta api Surabaya-Malang (1875-1879)
pada 20 Juli 1879. Jalur rel kereta api diperpanjang ke timur, yaitu dari Pasuruan
sampai Banyuwangi (PS 22/4/1918). Hal ini menandakan perubahan percepatan,
mobilitas, dan ketepatan.
Transportasi darat yang tidak kalah penting adalah jalur rel trem uap yang
dibangun oleh perusahaan kereta api lokal (Oost Java Stoomtram). O.J.S. didirikan
oleh W.A. Zilver Rupe dan A.J. Snouck Hurgronje pada 7 Juni 1888. Perbedaan OostJava Stoomtram (O.J.S.) dan Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij
(N.I.S.M.) terletak pada segi yuridis dan aktivitas beroperasi. Kereta api lokal dan
trem O.J.S. hanya menjangkau wilayah karesidenan tertentu, sedangkan kereta api
N.I.S.M. menempuh jarak lebih jauh antarkaresidenan (Knaap 1989:13). Trem uap
melalui jalur dalam dan luar kota, seperti Tarik (Mojokerto), Krian (Sidoarjo),
Sepanjang (Sidoarjo), Wonokromo, Kebun Raja (Stadstuin), dan Ujung. Panjang jalur
dari Sepanjang sampai Ujung kurang lebih 20 kilometer yang digunakan pada tahun
1889 dan 1890 (von Faber 1931:205 dan PS 13/9/1923). Kendala yang dihadapi oleh
O.J.S. terkait pembebasan lahan-lahan partikelir di beberapa kawasan Surabaya
Selatan. Pada tahun 1910 O.J.S. mulai mengerjakan jalan baru dari Wonokromo–
Kebun Raja yang diresmikan pada 1 Maret 1916 (PS 7/2/1916).
Pembangunan trem listrik (electrische trem) diajukan oleh O.J.S. pada 31 Desember
1910 kepada gubernur jenderal (PS 13/9/1923). Gagasan ini dilatarbelakangi oleh
kehadiran perusahaan listrik Algemeene Nederlandsche Electriciteit Maatschappij
(A.N.I.E.M.) pada tahun 1909. Akan tetapi, pembangunan rel dimulai dari
Wonokromo sampai Willemplein pada pertengahan tahun 1919 hingga 1923. Pada
bulan Juni 1923, trem listrik dibuka untuk publik, tetapi kehadirannya tidak
menghentikan trem uap karena terbukti tetap mengangkut penumpang hingga
tahun 1968 (PS 22/8/1919, 4/7/1923; Gpr 10/1968). Jalur pertama trem listrik
adalah dari stasiun Wonokromo (di sebelah utara Sungai Mas), Palmenlaan,
Simpang, Tunjungan, Kramat Gantung, Kebun Raja, Societeitstraat, Williemplein,
Grisseescheweg, dan Pelabuhan. Jalur keberangkatan kedua dimulai dari Stasiun
Gubeng, Celebesstraat, Konninginneweg, Sumatrastraat, kemudian melalui
Jembatan Gubeng, dan bertemu dengan jalur dari Wonokromo di Simpang. Dari
Simpang ini pula jalur trem listrik dipecah menjadi dua, yaitu dari Simpang ke arah
Utara menuju kota bawah dan ke arah Barat menuju Princesselaan (Jalan
Embongmalang) (PS 3/11/1921; 28/11/1922; 11/7/1923). Tempat duduk dibagi
dalam dua kelas, yaitu kelas satu 12 tempat duduk dan kelas dua 23 tempat duduk,
yang berada dalam satu gerbong (PS 31/12/1920 dan 3/11/1921). Antusiasme
masyarakat pada trem listrik dapat dilihat dari jumlah penumpang selama setengah
tahun sejak pembukaan seperti tampak pada Tabel 1.
pengguna trem listrik kurang lebih 10% per hari. Angka ini tidak termasuk jumlah
pengguna trem uap dan kendaraan pribadi, artinya mobilitas penduduk kota
tergolong tinggi, seperti kutipan “pada waktoe Stoomtram masih berdjalan dan
belon ada tram listrik, belon pernah djoemlah penoempang ada begitoe banjak” (PS
10/9/1923). Trem listrik sempat menimbulkan kekhawatiran angkutan umum lain
karena “sedjak ada tram terseboet, semoea kandara’an lainnja moendoer dengen
santer, jaitoe seperti kosong” (PS 10/9/1923). Penurunan jumlah penumpang (Tabel
1) terjadi pada penumpang kelas 1 yang sebagian besar ditempati oleh orang Eropa.
Penurunan ini disebabkan oleh kehadiran taksi, “dengen taxi orang brasa lebih
seneng, lantaran bisa toeroen di depan tempat jang ditoedjoe, sedeng dengen tram
listrik orang masih moesti djalan lagi” (PS 17/1/1924).
Beberapa jenis alat transportasi, seperti trem uap, trem listrik, bus, taksi, pedati, dan
kosong, telah meramaikan jalan di Kota Surabaya. Menurut Gerrit J. Knaap (1989:16),
kendaraan baru bermesin sebagai tanda kemajuan yang menuntut pengorbanan,
misalnya pedati dan kereta kuda, menjadi korban ekspansi kendaraan bermotor.
Dari tahun ke tahun, mobil semakin banyak melintas dan saling berpapasan di jalan
dengan kendaraan lain. Sejak pertengahan tahun 1910-an telah tersedia mobil sewa,
seperti tampak pada Gambar 1, sehingga orang tidak harus memiliki mobil jika
ingin mengendarainya.Iklan persewaan mobil (Gambar 1) yang dikelola oleh Liem Giok Tien dan Teng
Giok Tjiang menunjukkan pergeseran usaha jasa angkutan yang semula didominasi
persewaan kereta kuda. Persewaan kereta kuda kalah bersaing dengan persewaan
mobil, akibatnya “itoe satoe per satoe kosongan soedah disimpen sadja dan tiada
didjalanken. Malah ada dikabarken, bahoea banjak verhuurdery [persewaan] kosong
soedah ditoetoep” (PS 17/9/1920). Merasakan naik mobil menjadi lebih mudah
pada tahun 1920-an ketika hadir taksi yang dikelola oleh pemerintah, gemeente
taxidienst dan swasta, Maatschappij tot Exploitatie Taxi Onderneming (M.E.T.O.)
pada 1920 (PS 28/6 dan 9/10/1920). Kehadiran taksi juga disebut-sebut
menyebabkan berkurangnya kosong. Kendaraan kosong yang mangkal di stasiun
mulai enggan mengangkut penumpang Eropa yang tidak bersedia diangkut bersama. Hal ini terkait pada pendapatan yang lebih kecil dibanding mengangkut
penumpang Bumiputra yang bersedia diangkut bersama.
Peralihan sarana transportasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan
bermotor. Pada tahun 1922, jumlah kendaraan sebesar 6.065, terdiri atas mobil (auto)
4.288, truk (vrachtauto) 566, dan sepeda motor (motorfiets) 1.211 (PS 20/3/1922).
Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 1927 menjadi 8.290, terdiri atas mobil 5.973,
truk 685, sepeda motor 1.452, dan omnibus 180 (PS 5/1/1928). Selama lima tahun
(1922-1927) kendaraan bermotor di Kota Surabaya bertambah sebesar 36,7%.
Perubahan alat transportasi berpengaruh pada percepatan, mobilitas, dan
menimbulkan keluhan baru kemacetan. Ketika gerak kendaraan bertemu dalam satu
titik tertentu terutama di sisi perlintasan kereta api dan trem yang ditutup, maka
macet tidak dapat dihindari (PS 21/4/1923). Selain kendaraan darat sebagai wujud
kemajuan transportasi, muncul transportasi jarak jauh yang lebih cepat, yaitu
transportasi udara. Pada tahun 1920, alat transportasi baru diperagakan di udara
Kota Surabaya, sehingga menarik perhatian dan menjadi tontonan masyarakat,
“doea tukang terbang militer Luitenant Behrens dan De Ruyter soedah membikin
kalangan terbang di atas Soerabaia, kira lima menit lamanja kita bisa pandang itoe
pengliatan indah” (PS 30/6/1920). Penerbangan rintisan ini ditindaklanjuti dengan
lahirnya Eerste Nederlandsch Indische Vlieg Onderneming (ENIVO) (BS
20/8/1921).
Alat transportasi modern, seperti kereta api, mobil, dan pesawat terbang,
memperlancar perhubungan yang memungkinkan setiap orang dapat bepergian
lebih cepat. Perkembangan transportasi merupakan penjelasan faktual tentang kota
pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang bermakna sebagai tanda kemajuan
zaman dan membuktikan Surabaya sebagai kota modern
Permukiman Kota
Akibat yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan perkembangan transportasi
tampak pada perluasan permukiman. Perluasan permukiman kota juga dipengaruhi
oleh faktor lain, seperti pertokoan, jalan, dan pertambahan penduduk. Sekitar tahun
1860, muncul perkampungan baru dan toko-toko mengikuti radial jalan. Bagian
selatan kota, di sisi jalan yang membentang dari Simpang sampai Societeitstraat
berderet bangunan pertokoan berdiri berdampingan dan di belakangnya terdapat
perkampungan yang tumbuh semakin padat (von Faber 1931:44). Kelompok etnik di
Kota Surabaya pada pertengahan abad ke-18 dapat diklasifikasi berdasarkan
rumpun kebangsaan, yaitu Bumiputra, Cina, Arab, dan Eropa. Segregasi
antargolongan ditunjukkan oleh perbedaan permukiman yang tetap dipertahankan
meskipun tipologi kota telah berubah menjadi kota industri pada awal abad ke-20.
Sebelum kedatangan bangsa Barat, permukiman di Surabaya telah dimulai jauh
sebelumnya, seperti tampak pada Gambar 2.Gambar 2 tidak menyatakan nama permukiman atau kampung, tetapi ini menarik
perhatian jika dirujuk berdasarkan pendapat Sukadana yang menyebutkan bahwa
dari segi kewilayahan Surabaya berada di dataran rendah hilir Sungai Mas yang
berfungsi sebagai jalan masuk pelayaran ke pedalaman (Sukadana 1979:5). Menurut
G.H. von Faber (JP & PS 1/3/1952), di hilir sungai terdapat pelabuhan bernama
Dadungan yang ada sejak zaman Pu Sindok (929-948). Lokasi pelabuhan diduga
berada di sekitar Wonokromo dan diyakini sebagai faktor penting kemunculan
perkampungan. Nama tempat yang tergolong tua di muara sungai atau di deltadelta, di antaranya Gunungsari, Ngasem, Pumpungan, Pulo Wonokromo, Kupang,
Ujunggaluh, dan Pacekan. Tempat ini sampai saat ini masih menjadi nama kampung
(Timoer 1983:27-29). Peta sketsa hilir sungai dan delta-delta di Gambar 2
diperkirakan sudah berkembang menjadi perkampungan penduduk sejak abad ke-
10 yang bertepatan dengan perpindahan pusat Kerajaan Mataram Hindu dari Jawa
Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan kerajaan merupakan peristiwa besar yang
mengubah Jawa Timur menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Bukti kuat
tentang perubahan kawasan dapat dihubungkan dengan hilir dan delta Sungai Mas
yang dimanfaatkan sebagai lokasi terbentuknya perkampungan pada Airlangga
(1019-1042) (Cœdės 2010:202-6).
Perkampungan penduduk yang tergolong tua dikuatkan oleh bukti arkeologis dan
historis zaman Majapahit (Lbt 9/9/1961; 15/2/1964; Gpr 7-8/1968). Penelusuran
bukti-bukti dapat dimulai dari Prasasti Trowulan I berangka tahun 1358 dan Kitab
Negarakertagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365. Dua sumber ini
menyebutkan nama-nama yang diduga sebagai kampung, yaitu Terung (dekat
Krian wilayah Sidoarjo), Kambangan Sri atau Kembangsri (desa di Mojokerto), Teda,
Gesang atau Pagesangan, Bukul, dan Surabaya. Sampai sekarang nama-nama ini
masih menjadi nama kampung. Dalam prasasti Trowulan I tertulis, “[...] i trung, i kambangan çri, i tda, i gsang, i bukul, i çurabhaya, muwah prakãraning naditira
pradeça sthananing anãmbangi i madanten [...]” (Timoer 1983:13) dan “[...] di
Terung, Kambangan Sri, Teda, Gesang, Bukul, Surabaya, demikian pula halnya
desa-desa tepian sungai tempat penyeberangan seperti Madanten […].”
Bukti lain keberadaan kampung ditunjukkan oleh situs Ampel (pemakaman dan
masjid). Apabila suatu kawasan memiliki tempat pemakaman dan ibadah, maka
dapat dipastikan sebagai kawasan berpenghuni. Kawasan Ampel berkembang pada
pertengahan abad ke-15 ketika Raden Rahmat (Sunan Ampel) mengemban tugas
Raja Majapahit memperbaiki perilaku masyarakat di tempat itu. Hal ini berarti di
tempat itu telah terbentuk permukiman. Setelah Sunan Ampel meninggal, situs
pemakaman dan masjid menjadi tujuan peziarah muslim, sedangkan Kampung
Ampel menjadi konsentrasi tempat tinggal komunitas Arab berbaur dengan
Bumiputra.
Ketiga bukti yang disebutkan di atas, yaitu bukti geografis, peristiwa, dan situs,
menunjukkan kepastian adanya perkampungan di kawasan hilir Sungai Mas.
Kedatangan pedagang dari luar membuktikan Surabaya telah lama disinggahi,
bahkan dihuni oleh koloni-koloni asing berdampingan dengan penduduk lokal.
Perkembangan perkampungan pada abad ke-16 dapat dihubungkan dengan
kegiatan perdagangan. Pada saat itu, beberapa kapal pedagang dan kapal Portugis
yang melintasi Selat Madura singgah di Pelabuhan Gresik (de Jonge 1989:3-4),
karena lebih unggul dibanding Surabaya. Akan tetapi, pusat perdagangan beralih ke
Pelabuhan Surabaya sejak pengaruh Kerajaan Demak mulai melemah. Kondisi
politik ini juga dimanfaatkan oleh daerah kabupaten di kawasan pantai utara Jawa
untuk melepaskan diri dari hegemoni Kerajaan Demak (de Graaf dan Pigeaud
1985:18-26, 174, 196). Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi negara kota yang
kuat dalam menjalankan fungsi ideologis, administratif, politik, dan ekonomi secara
dominan dibanding kota lain di sekitarnya (Nas 1986b:18-36; de Graaf dan Pigeaud
1985:206).
Tata ruang kota terdiri atas beberapa unsur, seperti kraton, alun-alun, pasar, dan
perkampungan. Perwujudan Kraton Surabaya mengalami kerusakan parah setelah
perang dengan pasukan Sultan Agung pada 1625, sehingga struktur tata ruang
kraton dan perkampungan tidak dapat digambarkan secara detail. Kekuasaan
kraton yang melemah sejak peristiwa perang dan berdirinya perkampungan baru
secara alamiah menyebabkan bekas-bekas Kraton Surabaya terkikis. Kondisi ini
diperparah ketika VOC memilih membangun perangkat teknis pertahanan, benteng,
permukiman, dan aktivitas ekonomi di sebelah utara kraton. Penguasa lokal hanya
berkedudukan secara simbolik tanpa kewenangan besar dalam mengendalikan kota.
Akibatnya, bukti arkeologis kraton secara berangsur-angsur sirna dan peninggalan
yang tersisa hanya nama dan toponimi kampung (Lombard 2000:217, 222).
Pertumbuhan penduduk pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-18 dalam
keadaan lambat karena situasi politik tidak kondusif. Sebelum Sultan Agung (1613-
1645) menaklukkan Surabaya pada 1625, penduduk kota ditaksir 50.000 sampai 60.000 jiwa (de Graaf 2002:94-120). Jumlah ini menurun drastis setelah perang
selesai, yaitu kurang lebih 1.000 jiwa. Penurunan jumlah penduduk karena kematian
dan yang lebih besar karena migrasi untuk menghindari perang. Pada tahun 1706,
jumlah penduduk meningkat lagi hingga mencapai kurang lebih 20.000 jiwa. G.H.
von Faber (1931:16) mengibaratkan orang yang tinggal di Kota Surabaya bagaikan
hidup di gunung berapi yang dapat meletus setiap saat karena ketenangan
kehidupan kota masih terusik oleh pemberontakan. Kehadiran VOC sejak awal abad
ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 belum berperan mengubah kota karena hanya
menjalankan kegiatan ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan politik.
Perubahan model dan bentuk kota mulai terlihat ketika VOC memegang kendali
kekuasaan sejak tahun 1743 yang diperoleh melalui perjanjian politik dengan
Pakubuwono II (1726-1749). Pada tahun 1763, Surabaya ditetapkan sebagai tempat
kedudukan Gezaghebber in den Oosthoek. Penetapan ini secara bertahap berpengaruh
pada perubahan infrastruktur yang ditandai dengan pembangunan fasilitas
pertahanan dan pemisahan ketat tempat tinggal penduduk Bumiputra, Eropa, Cina,
dan Arab. Segregasi etnik ini tampak pada tahun 1787 (Gambar 4 Kiri), kemudian
pada tahun 1865, permukiman yang tersegregasi semakin meluas (Gambar 4
Kanan).
Gambar 4 menunjukkan komponen utama pertahanan didukung oleh pos jaga,
benteng, tembok keliling, gerbang, gudang mesiu, dan gudang amunisi, yang berada
di sebelah barat sungai. Fasilitas ini berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
Belanda. Tempat tinggal golongan Eropa berada di dalam tembok dan benteng,
sedangkan golongan lain berada di luarnya. Beberapa fasilitas pendukung yang ada
di kompleks adalah kantor, pergudangan, dan gereja. Pos jaga berfungsi sebagai
tempat penjagaan dan akses keluar masuk menuju permukiman eksklusif Eropa dan
tempat yang memudahkan pemantauan permukiman Cina di seberang sungai.
Segregasi etnik ditujukan untuk melindungi kepentingan Eropa dan mengawasi
golongan etnik lain yang ternyata menghambat terjadinya pembauran antaretnikSteele 1980:41). Kurang dari satu abad, pemerintah kolonial berupaya membangun
tembok kota dan benteng lebih luas dibanding sebelumnya.
Posisi permukiman Cina, Melayu, dan Arab, berada di luar garis batas (Gambar 4
kiri), lokasinya saling bersebelahan di sebelah timur Sungai Mas. Letak kampung
Bumiputra tersebar mengelilingi permukiman Eropa (Bleeker 1850:99-101). Proyek
infrastruktur pertahanan kota diperluas lagi pada tahun 1835. Model dan bentuk
sama dengan sebelumnya, yaitu benteng, tembok, dan parit yang melingkari pusat
kota (Gambar 4 Kanan). Jarak antara ujung utara sampai selatan kurang lebih 2.700
elo (1.854,9 m), sedangkan garis yang ditarik lurus dari timur ke barat kurang lebih
1.850 elo (1.270,9 m) (Tjiptoatmodjo 1983:246). Proyek pertahanan ini menggusur
beberapa kampung Bumiputra. Jumlah kampung yang terdapat di kawasan tembok
dan sekitarnya sebanyak 192, sedangkan kampung yang digusur sebanyak 54
kampung. Perkampungan ini dihuni oleh penduduk lokal. Dari jumlah yang tersisa
sebanyak 138 kampung, hanya 46 kampung yang berada di dalam tembok kota
(Basundoro 2013:75).
Menurut G.H. von Faber (1931:43, 45, 86), pembangunan benteng pertahanan kota
yang tidak tuntas menghambat perluasan kota sebab wilayah yang dibatasi oleh
tembok diibaratkan seperti ruang dalam sangkar. Residen S. van Deventer (1868-
1873) memutuskan membongkar tembok kota pada tahun 1871. Wilayah yang
dibatasi oleh garis-garis itu disebut kota bawah (benedenstad) atau kota lama. Istilah
benedenstad sebagai pembeda dari bovenstad (kota atas) yang berkembang pesat di
sebelah selatan pada awal abad ke-20, yaitu kawasan Simpang, Tunjungan, Darmo,
dan sekitarnya. Pembongkaran tembok kota berpengaruh pada pengembangan
kawasan permukiman ke arah selatan kota. Perluasan ini tidak serta-merta berjalan
lancar karena kendala kepemilikan tanah. Sebagian besar tanah di sebelah selatan
kota telah banyak dijual kepada pihak swasta pada masa Daendels dan Raffles,
sehingga statusnya berubah menjadi tanah partikelir. Menurut Adres-boek 1872,
penguasa tanah partikelir di bagian selatan kota terdiri atas para tuan tanah yang
berasal dari kalangan Cina, Arab, Eropa, dan Jawa (Anonim 1872:59).
Tuan tanah keturunan Arab adalah Sech Awal Mohammad bin Boebsaid, penguasa
tanah di Embong Malang, Sawahan, dan Kenjeran. Sederet nama keturunan Cina,
seperti Tjoa Djin Ho, Tjoa Djin Sing, dan Tan Tong Lip, menguasai tanah di
Keputran Kidul dan Kupang. Tan Bin Djang menguasai tanah di Wonokromo,
Dadungan, Karang Poh, dan sebagian persil di Kupang. Beberapa tanah yang
tersebar di selatan kota dikuasai oleh beberapa orang, seperti Ketintang milik Oei
Pik Tjioen, Karah milik Han Liong Kong, Tegalsari milik J. Jansen, Dinoyo milik Said
Alwi Alhabsi, Bubutan milik Schmilouw dan Matzen, Ketabang Selatan milik Han
Tian Ki, dan Ketabang Utara milik Han Tjian Kie. Tanah partikelir juga dimiliki oleh
bangsawan Jawa, misalnya Prawiro Adi Koesoemo menguasai tanah di Simo dan
Rekso Adi Koesoemo menguasai tanah di Petemon dan Kedung Anyar (Anonim
1872:59-60). Realitas kepemilikan tanah oleh para tuan tanah menyebabkan Kota
Surabaya sulit berkembang ke selatan selama abad ke-19 meskipun tembok kota
telah dibongkar dan parit-parit telah ditimbun. Perluasan permukiman kota ke selatan secara bertahap mulai terealisasi pada abad ke-20 ketika pemerintah pusat
memberi bantuan keuangan kepada gemeente untuk membeli kembali tanah
partikelir (Basundoro 2013:51).
Perluasan permukiman secara pesat berlangsung setelah penetapan Surabaya
sebagai gemeente pada 1 April 1906. Sebelumnya, yang disebut Kota Surabaya hanya
salah satu distrik setara Jabakota dan Gunung Kendeng, di bawah administratif
Kabupaten Surabaya. Walikota definitif baru ditetapkan pada 21 Agustus 1916
bertepatan dengan selesainya pembangunan kantor pemerintahan kota. Dengan
adanya walikota, kebutuhan perumahan dan perbaikan kampung terutama
pembenahan sanitasi mulai mendapat perhatian. Kawasan selatan kota berkembang
pesat menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan permukiman. Contohnya
adalah perumahan yang dibangun di Ketabang Utara dan Selatan pada dekade
kedua abad ke-20 merupakan hasil pembelian tanah partikelir oleh pemerintah
(ASGBB 1891-1942; PS 6/5, 3/6/1918). Kedua tanah itu dibeli dari Tan Tiang Kie dan
Tan Tjiang Kie. Proses serupa juga terjadi pada perumahan yang dibangun di
beberapa tempat, seperti Sawahan, Gubeng, dan Darmo. Rumah-rumah di kawasan
tersebut identik sebagai permukiman mewah golongan Eropa.
Area permukiman awalnya berfungsi sebagai lahan persawahan yang diubah atas
intervensi pemerintah kota hingga menjadi permukiman elite. Perkembangan
perumahan dilengkapi dengan fasilitas penting menyesuaikan standar hidup
modern. Perumahan yang dibangun lebih mengakomodasi tempat tinggal golongan
Eropa daripada Bumiputra, sehingga hanya golongan Eropa yang mampu membeli
rumah itu. Hal ini berarti pengorganisasian ruang permukiman selama abad ke-19
dan abad ke-20 tetap menerapkan prinsip etnisitas. Pola yang terbentuk masih mirip
permukiman pada akhir abad ke-18, yaitu pada saat dimulainya segregasi etnik.
Kampung-kampung Jawa tetap terhalang oleh pemandangan rapi deretan
perumahan modern di sepanjang jalan utama.
Komposisi Penduduk dan Masyarakat Kota
Perkembangan perekonomian kota (industri dan perdagangan) dan pembangunan
infrastruktur (jalan, transportasi, dan permukiman) berpengaruh terhadap
komposisi penduduk dan masyarakat kota. Ini disebabkan oleh peluang kerja yang
besar sehingga menarik minat orang bermigrasi. Pemilik modal swasta berpeluang
mengembangkan perkebunan, perdagangan, dan perusahaan karena didukung oleh
kebijakan liberalisasi ekonomi pada 1870. Hal ini menyebabkan perubahan populasi
dan komposisi penduduk kota. Golongan Eropa yang datang belakangan
terkonsentrasi pada bidang pekerjaan di perusahaan dan pemerintahan, tetapi
beraneka ragam pekerjaan lain juga tercipta, misalnya pengacara, konsultan, guru
privat, seniman, dan wartawan. Akibatnya, jumlah golongan Eropa di Kota
Surabaya mulai berubah, misalnya, penduduk Eropa pada tahun 1850 berjumlah
3.000, tahun 1.870 menjadi 4.500, dan tahun 1890 menjadi 7.500 (von Faber 1931:61).
Kenaikan jumlah penduduk berlangsung secara berkelanjutan hingga pemerintah
Hindia Belanda runtuh. Populasi golongan etnik lain tampak pada Tabel 2.Angka di Tabel 2 setidaknya dapat mewakili terjadinya perubahan jumlah
penduduk. Persentase jumlah penduduk menunjukkan kenaikan paling tinggi
terjadi pada kurun waktu tahun 1920 hingga 1930 sebesar 81,71%, kenaikan rata-rata
per tahun sebesar 8%. Orang Eropa mengalami kenaikan tinggi pada periode 1906
hingga 1920, yaitu kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9%, sedangkan periode
tahun 1930 hingga 1940 menunjukkan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 3%.
Kenaikan pesat jumlah orang Cina terjadi pada periode 1920 sampai 1930, yaitu
kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14%. Jumlah Bumiputra antara periode 1906
hingga 1920 mengalami kenaikan sebesar 19,23%, tetapi tidak dapat ditarik rata-rata
kenaikan per tahun karena terjadi banyak persoalan jika dicermati dari tahun ke
tahun dalam periode itu. Jumlah penduduk Bumiputra kurang detail. Pada tahun
tertentu pertumbuhan tampak lambat, bahkan pernah terjadi penurunan.
Perbandingan populasi dapat dilihat pada tahun 1906 dan 1913. Jumlah penduduk
kota sebesar 150.188 jiwa (tahun 1906) dan 133.632 (tahun 1913), sedangkan jumlah
Bumiputra 124.473 jiwa (tahun 1906) dan 123.584 jiwa (tahun 1913). Populasi
Bumiputra mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi buruk kesehatan
karena wabah penyakit pes tahun 1910 (von Faber 1936:297). Penyakit ini menjadi
persoalan serius yang mengakibatkan angka kematian tinggi terutama di kalangan
penduduk Bumiputra pada periode 1910 hingga 1920. Pada tahun 1916, jumlah
penduduk Bumiputra sebesar 124.291 jiwa (bandingkan dengan tahun 1906) dengan angka kematian sebesar 5.960 jiwa atau 4,79% (OH 2/2/1917; PS 7/2/1917).
Penurunan populasi juga dipengaruhi oleh pembangunan yang menggusur
kampung, “pendoedoek anak negri di ini kota soedah semangkin koerang lantaran
bebrapa kampoeng soedah dibeli boeat diriken gedoeng, hingga hilang ratoesan
orang boemipoetra ke paksa pindah di lain tempat” (PS 14/1/1914).
Komposisi penduduk yang disusun menurut klasifikasi etnik (Tabel 2)
memperlihatkan stratifikasi sosial berdasarkan etnisitas. Hal ini menjadi ciri khas
masa kolonial sekaligus sumber diskriminasi rasial dalam kehidupan
bermasyarakat. Kelompok etnik terstruktur secara hierarkis berdasar status sosial
dalam posisi atas, menengah, dan bawah. Lapisan atas ditempati oleh golongan
Eropa dan paling bawah adalah Bumiputra. Posisi di antara kedua golongan ini
ditempati oleh golongan Cina, Arab, dan Timur Asing. Penduduk Eropa terdiri atas
orang yang berasal dari Eropa (kebangsaan Belanda, Armenia, Belgia, Jerman,
Prancis, Inggris, Italia, Hongaria, dan lain-lain) dan keturunan campuran (von Faber
1936:35).
Kelompok Indo atau Indis menguat seiring dengan mantapnya kekuasaan Belanda.
Keturunan ini hasil dari perkawinan campuran dan tindakan menyimpang orang
Belanda yang memiliki gundik Bumiputra. Perilaku seperti ini masih ditemukan
pada abad ke-20 (BS 9/11/1912; PS 1/6/1914). Kehidupan Indo cenderung
mengikuti atau mengadopsi pola hidup Eropa (ke-Eropa-an) dibanding Bumiputra
(ke-Jawa-an), sehingga Indo disamakan dengan Eropa. Sebagian besar Indo bekerja
sebagai ambtenaar rendahan, tetapi posisi yang dipegang bertahun-tahun itu tidak
dapat dipertahankan setelah masa kemerdekaan. Golongan Indo yang tidak mampu
bertahan dan tidak sepenuhnya diterima dalam kehidupan bermasyarakat harus
eksodus dan menjadi warga negara Belanda merupakan sebuah pilihan (TM
20/6/1952).
Kelompok etnis lain (kebangsaan) adalah Cina, Arab, dan Timur Asing, yakni
imigran yang menempati kelas menengah dan bertempat tinggal secara terpisah di
bawah pemimpin sendiri. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta,
terutama kegiatan perdagangan. Orang Cina peranakan pada akhir abad ke-19
sudah tidak menggunakan bahasa Cina, tetapi berkomunikasi dengan bahasa
Melayu, bahasa sehari-hari masyarakat kampung, dan sebagian kecil berbahasa
Belanda. Fenomena ini menjadi perhatian seorang penulis seperti yang dimuat di
surat kabar (PS 18/11/1914) yang berbunyi ”kaloe saja pikir-pikir soenggoeh maloe
sekali orang peranakan Tionghoa, kebanjakan tiada mengerti hoeroef dan bahasa
TH.” Secara umum, golongan Cina memakai kombinasi istilah Tionghoa, Melayu,
dan Belanda.
Golongan Arab dikelompokkan dalam etnik tersendiri, sehingga golongan Timur
Asing adalah orang Asia selain Arab dan Cina. Orang Arab sudah bertempat tinggal
di Kampung Ampel sejak abad ke-17 (tahun 1680) yang dirintis oleh Syekh Awad
Boebsaid yang berasal dari Hadramaut (pantai selatan Arab antara Yaman dan
Oman). Peranakan Arab yang berkembang pada periode berikutnya diidentifikasi menjadi dua golongan genealogis, yaitu kelompok yang menyatakan diri sebagai
golongan alawiyyin atau sayid, beranggapan keturunan Nabi Muhammad dan bukan
sayid (Patji 1983:57). Mayoritas komunitas Arab bermatapencaharian sebagai
saudagar, berdagang, dan meminjamkan uang. Orang Arab yang berjualan
mindringan oleh orang Jawa disebut singkek Arab yang terkenal karena
meminjamkan barang dan uang dengan bunga tinggi (PB 29/6, 1/8/1896). Hal ini
menjadi perbincangan dan peringatan, seperti dikutip dari Bintang Soerabaia
(23/1/1904).
“Singkek-singkek Arab sekarang soeda moelai banjak lagi masoek
kloewar dalem kampoeng mendjalanken mindringan barang dan
oewang rentenan, itoe anak negri gampang sekali menarik hatinja
boewat pindjem apa apa sama Arab itoe jang mana achirnja keberatan
dirinja sendiri, inilah di koewatirkan keroesaken bagi anak boemi jang
koerang ingetan di blakang harinja.”
Lapisan bawah dalam kategori etnik adalah Bumiputra, yang didominasi oleh etnik
Jawa dan berbagai macam etnik, seperti Madura, Bali, Sulawesi, dan Ambon.
, stratifikasi sosial berubah sejak abad ke-20
dengan munculnya kelas sosial baru, yaitu pamongpraja Belanda, pegawai swasta,
pengusaha partikelir Eropa, akademisi, dan pengusaha ,Pekerjaan, pendidikan, peranan, kekayaan, jabatan, dan genealogi
menunjukkan perbedaan status sosial dengan penyebutan priyayi dan wong cilik
(kawula alit, rakyat jelata). Kelompok swasta bekerja atas inisiatif sendiri di sektor
perdagangan dan perusahaan, seperti ahli mesin, pelayan toko, hotel, restoran, dan
sopir, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan meningkatnya kontak dengan
dunia Barat. William H. Frederick (1989:28-30) mengklasifikasikan status sosial
Bumiputra di Kota Surabaya secara hierarkis tingkat bawah, menengah, dan atas.
Golongan tingkat bawah adalah rakyat jelata, tingkat menengah dikenal dengan
istilah kaum cukupan yang ditetapkan dari kriteria ekonomi, yaitu pengusaha,
pedagang, pegawai, tukang, dan buruh berkeahlian khusus. Stratifikasi sosial atas
adalah priyayi, yaitu kelompok yang bergelar bangsawan dan yang mempunyai
kedudukan pada profesi-profesi modern, seperti dokter, pengacara, dan guru.
Meskipun beberapa profesi-baru bermunculan, mayoritas Bumiputra yang
didominasi oleh etnik Jawa masih menggantungkan matapencaharian di sektor
pertanian dibanding pedagang dan pegawai administratur. Seiring dengan
longgarnya kehidupan sosial di kota, tampaknya kelompok priyayi masih
dikategorikan sebagai elite. Ini menunjukkan perubahan kota pada pergantian abad
ke-20 terjadi secara menyeluruh, misalnya ekonomi, teknologi, infrastruktur,
penduduk, dan sosial.
Kemajuan Kota Surabaya sekitar awal abad ke-20 telah mengubah status kota
menjadi kota kolonial modern yang ditunjukkan oleh munculnya simbol
modernitas. Simbol modernitas menjadi pembeda karakteristik fisik kota, yaitu
industri, alat transportasi, dan permukiman. Perkembangan pesat industri
menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan ekonomi dan pola bekerja. Dari
perubahan ini ditemukan bahwa masyarakat kota tidak hanya bertumpu pada
pertanian dan perdagangan, tetapi juga sektor-sektor lain khususnya industri.
Perkembangan industri di Kota Surabaya meliputi berbagai jenis pabrik skala besar
dan kerajinan. Sektor kerajinan dikategorikan sebagai industri karena memproduksi
barang secara berkesinambungan. Unsur lain yang menunjukkan kemajuan kota
adalah perubahan alat transportasi modern. Kendaraan modern mendukung
percepatan distribusi barang dan mobilitas semakin tinggi. Sejak kehadiran alat
transportasi modern, terjadi perubahan jasa angkutan. Kendaraan yang dianggap
kuno digeser oleh kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan mobilitas penduduk
kota semakin tinggi, sehingga populasi kota semakin menigkat dari tahun ke tahun.
Kemajuan kota juga menghasilkan perubahan stratifikasi masyarakat. Setiap orang
memiliki peluang menempatkan status sosial di masyarakat melalui persaingan
terbuka, misalnya pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Mobilitas vertikal baru
dapat diraih pada awal abad ke-20.










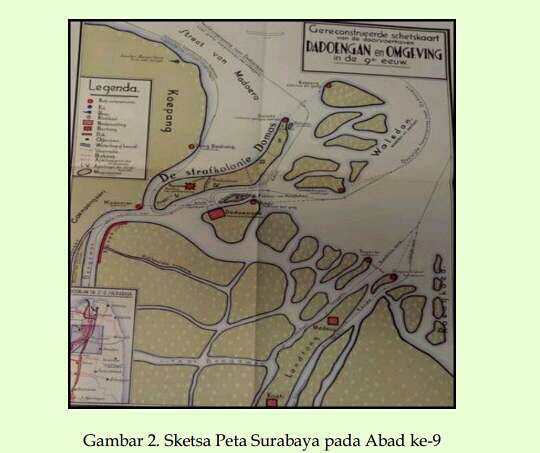











.jpg)





