Tampilkan postingan dengan label bangunan zaman belanda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bangunan zaman belanda. Tampilkan semua postingan
bangunan zaman belanda
wajah Indonesia secara keseluruhan. Dalam banyak aspek kehidupan, kolonialisme dianggap lebih
banyak memberikan efek negatif daripada efek positif karena memunculkan banyak korban jiwa
dan harta benda. Demikian pula pada bidang arsitektur khususnya permukiman.Permukiman
kolonial Belanda di Indonesia terlihat berbeda dengan permukiman lokal, hal ini disinyalir karena
permukiman kolonial Belanda lebih mendasarkan dirinya pada pertimbangan-pertimbangan logis
dibandingkan dengan permukiman untuk masyarakat lokal yang relatif menonjolkan lebih banyak
aspek budaya maupun kosmologi. Adapun beberapa pertimbangan logis yang dimaksud disini
adalah kelengkapan infrastruktur, kesehatan lingkungan, serta aspek kenyamanan yang lebih
terjamin. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemilihan lokasi untuk permukiman kolonial Belanda
di Indonesia yang tidak berbaur dengan etnis lain. Dengan demikian maka kehadiran permukiman
kolonial Belanda semakin memarginalkan permukiman tradisional yang telah ada sebelumnya,
terlebih setelah diterapkannya beberapa kebijakan yang mengatur masalah tata wilayah seperti
wijkenstelsel (permukiman berdasarkan etnis), decentraliewet (desentralisasi pemerintahan),
stadvormingordonantie (pembangunan perkotaan), dan lain-lain.
Jawa pada masa kolonialisasi Belanda memegang peranan penting sebagai pusat dari
pemerintahan maupun ekonomi. Oleh karenanya tidak heran jika pembangunan pada masa
penjajahan Belanda banyak dilakukan di Jawa. Dalam bidang permukiman, migrasi penduduk
Eropa ke Indonesia membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kemajuan maupun pemekaran
kota dengan dibukanya daerah-daerah baru untuk permukiman bagi orang-orang Eropa khususnya
Belanda. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki melahirkan pendekatan efektif dan efisien yang
salah satunya diwujudkan dalam pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam rangka
menyediakan permukiman dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat khususnya
setelah diterapkannya Politik Etis dan Decentraliewet. Selain itu kebutuhan untuk menghadirkan
rasa aman dan nyaman melalui penyesuaian diri dengan iklim dan lingkungan setempat membawa
pembaharuan pada wujud arsitektur permukiman Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia. Hal
tersebut dapat dilihat pada kemunculan Arsitektur Indo Eropa atau yang sering disebut sebagai
Arsitektur Indis. Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya kehadiran orang-orang Eropa khususnya Belanda
ke Indonesia yang semula hanya sekedar berdagang berubah menjadi ingin menguasai komoditas
dagang dan hal ini kemudian memunculkan praktek kolonialisasi yang selanjutnya mempengaruhi
kebudayaan asli hingga memunculkan kebudayaan baru yang belum pernah ada sebelumnya yaitu
kebudayaan indis. Lebih lanjut Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya kebudayaan Indis
tercermin pada berbagai macam elemen fisik maupun non fisik termasuk didalamnya adalah
arsitektur.
Sejarah perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia telah dimulai sejak VOC
memulai aktivitas perdagangannya pada tahun 1602 dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial
Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai dengan 1942. Selama praktek kolonialisasi Belanda di
Indonesia, Arsitektur kolonial telah berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan politik
penjajahan dan kebudayaan yang diberlakukan oleh Belanda (Soekiman, 2011: 21-38). Senada
dengan Soekiman, Silas (2005) berpendapat bahwa wujud arsitektur yang paling responsif
terhadap perubahan adalah rumah tinggal, oleh karena itu maka dengan mengamati
perkembangan arsitektur permukiman kolonial di Indonesia, kita bisa mengetahui bagaimana
Arsitektur kolonial yang dibawa dari Eropa berkembang di Indonesia dengan pendekatan formal
dan rasional sehingga menjadi arsitektur yang responsif terhadap keadaan lingkungannya.
Selanjutnya, Suptandar (2001), Silas (2005), De Vletter (2009), maupun Soekiman (2011)
sepakat bahwasanya peran dari Arsitektur kolonial yang diterapkan di Indonesia khususnya Jawa
adalah sebagai simbol kekuasaan dari kolonialisasi Belanda, dan secara perlahan namun menjadi
simbol identitas yang diikuti oleh masyarakat lokal agar dapat dekat dengan penguasa, inilah cara
bagainana pendekatan arsitektur dan tata kota ala barat mempengaruhi arsitektur dan tata kota
lokal.
B. Arsitektur Kolonial, Pembangunan, dan Modernisasi Arsitektur di Indonesia
Pada sub bab ini dan seterusnya akan diperbandingkan pendapat dan teori mengenai
perkembangan umum arsitektur kolonial Belanda di Indonesia dari 6 buah artikel dalam buku atau
buku yang ditulis oleh 5 orang peneliti arsitektur yang berbeda. Selain itu juga akan dikaji artikel
lain sebagai penunjang atau tambahan dari isi tulisan ini. Lebih detail mengenai judul artikel atau
buku dan nama penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Daftar Tulisan Yang Digunakan Sebagai Rujukan Utama
No. Nama Penulis Tahun Judul Artikel dalam Buku / Buku
1. Johannes Widodo 2007 Arsitektur Indonesia Modern: Transplantasi,
Adaptasi, Akomodasi, dan Hibridisasi
2. Cor Passchier 2007 Arsitektur Kolonial di Indonesia Rujukan dan
Perkembangan: Masa lalu Dalam Masa Kini
Arsitektur Indonesia
3. Handinoto 2010 Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa
Kolonial
4. Cor Passchier 2012 Mencari Arsitektur Indonesia yang Utama Pada
Masa Akhir Kolonial: Tegang Bentang
5. Amir Sidharta 2012 Ketengangan dan Perdebatan dalam Sejarah
Arsitektur Modern Indonesia
6. Emile Leushuis 2014 Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka di Indonesia
Sumber: Wihardyanto, 2019
Dari keenam tulisan yang dikaji, semua peneliti membagi periode perkembangan Arsitektur
Kolonial di Indonesia berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pembangunan di Pulau
Jawa pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pulau Jawa digunakan sebagai representasi
dari Indonesia karena sebagian besar pembangunan maupun kebijakan politik, ekonomi, sosial,
dan budaya yang diterapkan oleh Belanda mengacu pada kondisi yang ada di Pulau Jawa. Hal ini
mengakibatkan kondisi Pulau Jawa tampak berbeda dengan pulau lainnya di Indonesia dalam hal
kemajuan pembangunan. Salah satu contohnya adalah sebagian besar jalur kereta api di Indonesia
terdapat di Pulau Jawa yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi
dari pedalaman menuju pelabuhan. Oleh karena itu maka dengan mengamati perkembangan
Arsitektur Kolonial Belanda di Jawa diharapkan dapat mewakili sebagian besar dari perkembangan
Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia.
Dari kajian literatur yang dilakukan, diketahui bahwasanya periode perkembangan
Arsitektur Kolonial dapat dikategorikan menjadi 2 fase, fase pertama yang berlangsung antara
tahun 1602 M s.d. 1799 M dan fase kedua berlangsung antara tahun 1800 M samap dengan 1942 M.
Pembagian fase tersebut tampaknya didasarkan pada perbedaan orientasi maupun visi misi dari
pendudukan Belanda di Indonesia khususnya Jawa. Pada fase pertama, semua peneliti sepakat
bahwasanya Belanda belum melakukan pembangunan yang terencana di Indonesia karena VOC
memfokuskan pada usaha monopoli perdagangan, sedangkan pada fase kedua Pemerintah Kolonial
Belanda telah melakukan pembangunan yang terencana karena telah berorientasi kepada
penguasaan wilayah beserta sumber dayanya (kolonialisasi).
Dikarenakan orientasi yang lebih difokuskan pada perdagangan maka wujud Arsitektur
Eropa yang muncul di Indonesia pada masa VOC terbatas pada pos perdagangan berupa benteng,
dan rumah-rumah merangkap gudang penyimpanan bergaya Klasik Eropa yang terdapat di daerah
sekitar benteng. Wujud arsitektur tersebut berbeda dengan arsitektur lokal yang ada dan belum
pernah dibangun di Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu maka Widodo (2007), dan Sidharta
(2012) menyebutkan modernisasi arsitektur di Indonesia dimulai pada masa ini (disebutkan
sebagai Masa Modern Awal). Lebih lanjut Widodo (2007) menyatakan bahwasanya sebelum abad
ke-19 bangunan bergaya arsitektur Eropa masuk dan berkembang di Indonesia dengan cara
transplantasi arsitektur yakni dengan menerapkan mentah-mentah arsitektur Eropa di Indonesia
tanpa sebelumnya dikontekstualisasikan terlebih dahulu. Benteng maupun bangunan lain didirikan
dengan cara meniru apa yg dibangun di Eropa atau Belanda tanpa adanya penyesuaian terlebih
dahulu (Gambar 1). Berbeda dengan yang terjadi pada abad ke 19 dan setelahnya dimana
penerapan Arsitektur Eropa di Indonesia telah terlebih dahulu mengalami proses pemikiran
mendalam mengenai proses adaptasi, akomodasi, serta fusi. Hal senada ditambahkan oleh Sidharta
(2012) yang menjelaskan bahwa pada abad ke 19 Arsitektur Eropa diterapkan di Indonesia melalui
proses adaptasi dan akulturasi. Lebih lanjut Sidharta (2012) berpendapat bahwasanya dibidang
permukiman, VOC tidak memiliki perencanaanpembangunan permukiman karena orientasi
kegiatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya dalam waktu
cepat. Berbeda dengan masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mulai merencanakan
permukiman secara sistematis. Salah satu indikasinya adalah mulai adanya gambar-gambar
rencana perluasan kota yang didalamnya terdapat rencana pengembangan kawasan permukiman
kolonial.
bahwasanya modernisasi arsitektur di Indonesia
belum terjadi pada masa VOC, melainkan baru terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia
Belanda. Hal ini terlihat pada tidak adanya label modern yang diberikan pada kurun waktu tahun
1602 sampai dengan 1799 oleh para peneliti tersebut. Para peneliti tersebut menguraikan
beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa modernisasi arsitektur baru terjadi pada saat
Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, yang pertama adalah adanya pembangunan yang
lebih tersistematis dan memiliki landasan. Kedua adalah adanya beberapa kebijakan sosial politik
seperti misalnya Politik Liberalisasi, Politik Etis, serta Politik Desentralisasi yang selain
mempercepat arus barang, jasa, dan manusia, juga mempercepat informasi masuk dari Eropa ke
Indonesia sehingga muncul paradigma baru dalam pembangunan. Penulis berpendapat
bahwasanya kemunculan gerakan modernisme di Eropa merupakan salah satu yang berpengaruh,
dimana paradigma arsitektur yang lebih terukur mengikis romantisme arsitektur zaman klasik.
Salah satunya dengan lebih mengedepankan aspek fungsi daripada dekorasi serta lebih
mengeksplorasi penggunaan material dan teknologi fabrikasi. Lebih lanjut, dengan memahami uraian dari Handinoto (2010), Passchier (2007 dan 2012),
serta Leushuis (2014), penulis berpendapat bahwasanya peralihan kekuasaan dari VOC kepada
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga membawa perubahan orientasi pembangunan yang
ditandai dengan adanya usaha untuk membangun konektifitas darat antar wilayah di Indonesia
alih-alih jalur laut. Hal tersebut dapat dilihat pada masa VOC daerah-daerah yang maju adalah
daerah-daerah pesisir yang memiliki pelabuhan dan jalur perdagangan antar pulau untuk
memfasilitasi memonopoli perdagangannya. Sebaliknya daerah pedalaman sebagai pusat produksi
pertanian dan perkebunan kurang mendapatkan perhatian karena sulitnya akses. Artefak fisik
yang dapat kita lihat adalah banyaknya benteng-benteng dibangun di tepi laut atau muara sungai
sebagai pos perdagangan VOC. Berbeda dengan masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda
dimana konektifitas antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman atau antar daerah pedalaman
mulai ada dengan dibangunnya jalan pos besar (De Grote Postweg)Anyer - Panarukan, serta jalur
kereta api. Dampak dari adanya jalur pos maupun jalur kereta api tersebut adalah mulai
terbukanya daerah-daerah baru dipedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh dan dengan
terbukanya daerah baru ditambah arus barang, jasa, dan manusia yang semakin lancar maka
pembangunanpun akan semakin merata dan kebutuhan akan permukiman semakin besar.
Pernyataan tersebut didukung oleh Passchier (2007) bahwa fase modernisasi arsitektur di
Indonesia dimulai dari penerapan beberapa kebijakan kolonialisasi seperti misalnya cultuurstelsel
(tanam paksa), dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan itu maka diperlukan pembangunan
infrastruktur jalan yang dimulai dari pembangunan De Grote Postweg dan dilanjutkan dengan
pembangunan jalur kereta api.
Pembangunan di Indonesia dirasa semakin pesat setelah adanya pemberlakukan Politik Etis
yang kemudian disusul oleh pemberlakuan Agrarischewet (Undang-Undang Liberalisasi Agraria),
dan Decentraliewet. Penerapan politik, serta undang-undang tersebut berkorelasi terhadap
meningkatnya jumlah industri baik industri sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor-sektor
lainnya (Soekiman, 2011). Dengan demikian maka terjadi pula lonjakan penduduk Eropa yang
masuk ke Indonesia dalam rangka berinvestasi ataupun bekerja, dan hal ini menyebabkan lonjakan
kebutuhan permukiman dalam skala besar. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda dalam rangka penyediaan dan pembangunan permukiman adalah dengan
diadakannya Konggres Perumahan Rakyat tahun 1922 yang terkenal dengan diskusi yang hangat
antara Ir. Herman Thomas Karsten dan Ir. C.P. Wolff Schoemaker mengenai perbedaan peran
pemerintah dalam penyediaan kebutuhan permukiman yang sehat bagi semua golongan Warga
Hindia Belanda.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, didapatkan informasi bahwasanya kehadiran
arsitektur kolonial Belanda di Indonesia sebagai momentum modernisasi arsitektur di Indonesia
dapat ditinjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah arsitektur kolonial Belanda sebagai sebuah
produk arsitektur yang wujudnya sama sekali berbeda dan sebelumnya belum pernah ada
misalnya adalah benteng dari bahan batu atau batu bata seperti yang terdapat di Eropa.Sisi yang
kedua adalah arsitektur kolonial Belanda ditinjau dari paradigma yang menghasilkan prinsipprinsip arsitektur baru yang lebih modern tanpa mengesampingkan arsitektur yang sudah ada
sebelumnya, misalnya adalah Arsitektur Indis pada bangunan rumah tinggal.
Penulis sendiri lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya modernisasi
arsitektur di Indonesia terjadi pada masa Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa. Hal ini
dikarenakan pada masa VOC, pembangunan arsitektur belum dilandasi oleh suatu pemikirankomprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan fungsi, struktur, konteks sosial, dan
lingkunganserta tidak berlandaskan aturan tertentu.
C. Perkembangan Permukiman Kolonial di Indonesia Masa VOC
Pada masa VOC pembangunan dilakukan untuk menunjang perdagangan dan pengangkutan
komoditas dari Indonesia menuju Belanda. Sidharta (2012) menjelaskan bahwasanya pada masa
VOC, orang-orang Eropa khususnya Belanda umumnya tidak memiliki keinginan untuk menetap di
Indonesia karena mereka umumnya adalah pedagang dan militer yang ditugaskan untuk
memonopoli komoditas pertanian dan perkebunan untuk dibawa dan diperdagangkan di Eropa.
Handinoto (2010) menambahkan bahwasanya guna mendukung usaha tersebut maka VOC
membangun pos-pos perdagangan yang tidak jarang dilengkapi fasilitas keamanan berupa benteng
di daerah pesisir dan membangun konektifitas melalui jalur laut diantara pos-pos perdagangan
tersebut. Senada dengan Handinoto (2010), Leushuis (2014) menekankan bahwa benteng
merupakan titik pertumbuhan arsitektur kolonial pada masa VOC. Jika perdagangan didaerah itu
ramai atau strategis maka benteng juga akan semakin besar dan tidak jarang tumbuh pemukiman
kolonial disekitarnya. Penjelasan tambahan mengenai hal ini dapat diketahui dari Buku Fort in
Indonesia yang diterbitkan tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia yang menjelaskan bahwasanya untuk menunjang kesuksesannya, VOC terlibat pada
intrik politik atau suksesi kerajaan lokal dengan imbalan mendapatkan hak monopoli perdagangan
dan tanah yang kelak berkembang sebagai daerah permukiman bagi orang-orang Eropa atau
daerah pertanian dan perkebunan yang berstatus sebagai tanah partikelir.
Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, penulis merujuk pada pernyataan
Passchier (2007) yang meskipun tidak secara tegas, membagi pembangunan pada masa VOC
menjadi 2 periode yaitu periode Benteng (1600 s.d. 1750an) dan periode Di Luar Benteng (1750 -
1799). Pada periode benteng, keamanan komoditas dan kelancaran pengiriman menjadi hal yang
utama, sehingga aspek sekuritas dan fungsionalitas perdagangan menjadi penting. Kenyamanan
tinggal untuk orang-orang yang bekerja pada sektor perdagangan tidak dianggap prioritas karena
seakan-akan mereka menilai dirinya hanya transituntuk mengambil barang dagangan. Oleh karena
itu mereka merasa cukup untuk tinggal di dalam benteng tersebut. Hanya jika perdagangan
semakin maju dan VOC memiliki kekuasaan lebih atas tanah pesisir maka mereka dapat
membangun permukiman di luar benteng namun lokasinya tidak terlalu jauh atas pertimbangan
keamanan.
Passchier (2007), Raap (2015), dan Handinoto (2010) memberikan penjelasan tambahan
mengenai kawasan permukiman dan bentuk arsitekturnya.Mereka menjelaskan bahwasanya
kawasan benteng dan permukiman orang-orang Belanda cukup jauh dari permukiman lokal yang
umumnya didaerah pedalama.Apalagi setelah terjadinya peristiwa pemberontakan Cina di
Tangerang, kebijakan pemisahan permukiman Eropa dengan bangsa lain semakin diperketat
dengan penerapan politik wijkenstelsel dan passenstelselyaitu penerapan kebijakan pelaporan dan
biaya keluar masuk wilayah tertentu (Gambar 2). Ketiga penulis diatas juga menjelaskan
bahwasanya bentuk rumah bergaya Eropa dua lantai yang efisien mirip dengan gaya arsitektur di
kota-kota besar di Belanda juga ditemukan di kota-kota besar di Hindia Belanda lengkap dengan
parit atau kanal-kanal yang selain berfungsi sebagai jalur transportasi juga berfungsi sebagai
sanitasi dan keamanan.
Cor Passchier (2007) secara spesifik menyebutkan bahwasanya ruang-ruang atau bangunan
di dalam benteng, termasuk di dalamnya untuk fungsi permukiman dibangun dengan pola grid
untuk lebih memaksimalkan faktor keamanan karena pengawasan, dan mobilisasi tentara akan
lebih mudah, hal ini seperti yang dianjurkan oleh penasihat militer Pangeran Oranye yaitu Simon
Stevin (1548-1620). Lebih lanjut Passchier (2007) menjelaskan bahwa pola grid ini juga
diterapkan untuk permukiman kolonial di sekitar benteng dengan maksud dan tujuan yang sama serta mempermudah pembangunan kanal yang salah satu tujuannya adalah sebagai saluran air
kotor. Sedikit berbeda dengan periode benteng, pada periode luar benteng, Passchier (2007)
menjelaskan bahwa VOC mulai membuka akses secara terbatas ke daerah pedalaman. Disini
mereka memanfaatkan tanah hadiah dari penguasa lokal sebagai tanah partikelir yang disewakan
atau diperjualbelikan kepada pengusaha Belanda. Pada periode ini mulai tumbuh rumah-rumahlandhuis, yaitu rumah besar yang memiliki lahan yang sangat luas karena diperuntukkan juga bagi
pertanian atau perkebunan beserta fasilitas pendukungnya seperti misalnya tempat tinggal untuk
budak. Sebagai keterangan tambahan, Gill (1998) menggambarkan landhuis ini sebagai rumah
berasitektur campuran yang berukuran besar, berada ditengah-tengah perkebunan, memiliki akses
jalan ke pelabuhan, serta jauh dari pemukiman lokal (Gambar 3).
Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya sifat
permukiman kolonial pada masa ini cenderung tertutup dan eksklusif. Mereka membangun dengan
mentransplantasikan (mencangkokkan) gaya arsitektur Eropa, memposisikan permukimannya
jauh dari permukiman lokal dan menyediakan segala sesuatunya khusus untuk kebutuhan mereka
sendiri. Kesemuanya dikelola dalam pola permukiman berbentuk grid.
D. Perkembangan Permukiman Kolonial Di Indonesia Masa Pemerintah Kolonial Belanda
Perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial
Belanda semakin pesat. Hal ini menurut Sidharta (2012) dilatarbelakangi oleh kebangkrutan VOC
dan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan demikian maka terjadi perubahan
orientasi Belanda yang semula hanya berdagang menjadi menguasai sumber daya alam untuk
jangka waktu yang panjang (kolonialisasi). Untuk menunjang kolonialisasi tersebut perlu disusun
sistem pemerintahan dan ekonomi yang memerlukan rencana pembangunan yang sistematis,
termasuk didalamnya adalah penyediaan permukiman kolonial beserta fasilitas pendukungnya.
Mulai adanya rencana pembangunan yang sistematis inilah yang dinyatakan oleh Passchier
(2007) sebagai titik mula modernisasi pembangunan di Indonesia. Lebih lanjut Passchier (2007)
maupun Handinoto (2010) menjelaskan bahwa untuk mengawalinya pemerintah kolonial Belanda
terlebih dahulu meningkatkan keamanan sekaligus memeratakan arus barang, jasa,dan manusia di
daerah dengan cara membangun infrastruktur jalan antar daerah khususnya di Pulau Jawa.
Pembangunan De Grote Postweg dari Anyer hingga Panarukan tahun 1808 dapat dikatakan sebagai
proyek yang strategis meskipun memakan korban jiwa yang banyak. Karena adanya jalan ini maka
kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa dapat terhubung dan menciptakan konektifitas
yang cukup kuat dari sisi keamanan, dan ekonomi. Diduga adanya jalan raya pos ini menjadi salah
satu pertimbangan Pemerintah Kolonial Belanda optimis menerapkan kebijakan cultuurstelsel pada
tahun 1830 karena jalur pengangkutan menuju pelabuhan dan selanjutnya diangkut menuju ke
negeri Belanda semakin mudah. Selain itu dengan adanya proyek ini, tumbuh pula beberapa kota
baru sebagai penyokong kota pelabuhan yang sudah ada sebelumnya.
Selanjutnya untuk lebih memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur jalan yang
sudah ada serta membuka daerah pedalaman sebagai pusat pertanian maupun perkebunan baru
maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun jaringan jalan kereta api yang dimulai pada
tahun 1873 dengan jalur Semarang-Tanggung. Tujuan utama dari adanya jalur-jalur kereta api ini adalah untuk memudahkan jalur pengangkutan hasil bumi dari daerah pedalaman menuju stasiun
pelabuhan untuk kemudian dikapalkan, namun demikian lambat laun dikembangkan pula untuk
pengangkutan manusia karena tingginya permintaan. Keberhasilan dari pembangunan jalur kereta
api tampaknya berkorelasi pada perkembangan ekonomi disuatu wilayah maupun kota di
Indonesia khususnya di Pulau Jawa, hal ini seperti yang diuraikan oleh Handinoto (2010) dan
Leushuis (2014). Penulis berpendapat bahwasanya kehadiran kereta api di daerah pedalaman
turut mendorong migrasi orang-orang Eropa menuju pedalaman untuk mengembangkan usahanya.
Lama-kelamaan migrasi tersebut menyebabkan munculnya permukiman kolonial di daerah
pedalaman. Handinoto (2010) memberikan penjelasan tambahan bahwasanya keberadaan jalurjalur kereta api seringkali menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengembangan kota ataupun
permukiman kolonial.
Menjelang abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Politik Etis (1902) dan
beberapa kebijakan yang nantinya akan mendorong pertumbuhan permukiman bagi masyarakat
Eropa lebih pesat. Kebijakan tersebut adalah agrarischewet yang diterapkan tahun 1870-1942 dan
decentralisatiewet yang diterapkan tahun 1903-1942. Handinoto (2010), Sidharta (2012),
Passchier (2012), dan Leushuis (2014) sepakat menyatakan bahwa setelah penerapan Politik Etis
sampai dengan tahun 1942 sebelum penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang, pertumbuhan
permukiman bagi orang-orang Eropa lebih pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada
periode ini jumlah kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia mengalami peningkatan yang
signifikan dengan latar belakang mereka yang bermigrasi ke Indonesia pun semakin beragam. Hal
ini mendorong pembaharuan di segala aspek kehidupan di Indonesia akibat masuknya paradigma
baru ditengah-tengah paradigma yang sudah ada Surjomihardjo (2008).
Migrasi yang cukup besar dari orang-orang Eropa selanjutnya mendorong Pemerintah
Kolonial Belanda untuk memikirkan bagaimana menyediakan permukiman yang sehat dalam
jumlah yang banyak. Oleh karena itu pemerintah mencoba merencanakan dan membangun
kawasan permukiman kolonial baru di luar kota melalui suatu pola kemitraan publik-privat. Hal ini
seperti yang diuraikan oleh Handinoto (2010), setelah tahun 1900-an Pemerintah Kolonial Belanda
mulai melakukan perencanaan pengembangan kota di Indonesia secara menyeluruh terutama
mengenai pembangunan kawasan hunian baru yang lebih baik dari segi kesehatan dan kesesuaian
dengan iklim dan lingkungan setempat dengan mengadaptasikan prinsip-prinsip arsitektur lokal
kedalam perancangannya. Leushuis (2014) menambahkan bahwasanya Pemerintah Kolonial
Belanda banyak memanfaatkan tanah-tanah partikelir yang berada diluar kota sebagai kawasan
permukiman kolonial baru yang lebih sehat (Gambar 4).
Dengan beberapa pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwasanya perancangan
permukiman kolonial baru ini lebih sehat karena mendapatkan kualitas lingkungan dan udara yang
lebih baik, memiliki infrastruktur yang lebih lengkap karena direncanakan dan dibangun dengan
perhitungan yang matang, serta lebih terjangkau karena memiliki harga tanah yang lebih murah
dibandingkan di pusat kota. Tidak lupa prinsip garden city ala Ebenezer Howard yang saat itu
tengah populer di Eropa dan Amerika bisa diterapkan karena ketersediaan lahan yang
memungkinkan. Namun demikian, menurut Leushuis (2014) dan Passchier (2012), pola grid
tampaknya tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan permukiman kolonial baru tersebut.
Penulis menduga bahwasanya pola grid sangat efektif dan efisien untuk pembangunan
infrastruktur penunjang permukiman.Lebih lanjut Passchier (2012) menyatakan bahwasanya pemerintah menggandeng pihak
swasta untuk memenuhi kebutuhan permukiman setelah tahun 1900-an, terutama setelah
pemberlakukan decentraliewet. Pemerintah pusat memposisikan diri sebagai regulator yang
memiliki tugas untuk menyiapkan rencana pengembangan permukiman, dan mengatur regulasi
pendukungnya, pemerintah daerah bertugas untuk serta menyiapkan lahan, serta membangun
infrastruktur permukimannya, sedangkan pihak swasta berperan sebagai pengembang dan
memasarkan. Oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa tidak heran jika kawasan maupun
arsitektur permukiman kolonial ketika itu selain harus memenuhi kriteria sehat dan sesuai dengan
iklim setempat juga harus dibangun dengan gaya perancangan yang paling modern ketika itu agar
mudah dijual (Gambar 5).
Sidharta (2012) mengingatkan bahwa adanya Kongres Perumahan Rakyat pada tahun 1922
tidak dapat dikesampingkan pada perkembangan pembangunan permukiman saat itu. Adapun
tema diskusi pada konggres tersebut adalah penyediaan hunian yang sehat yang terjangkau.
Dimulai dari pemilihan lahan yang tepat untuk permukiman, ketersediaan infrastruktur dasar
penunjang permukiman yang cukup, serta arsitektur rumah tinggal yang sesuai terhadap iklim dan
lingkungan lokal. Passchier (2012) menambahkan bahwa alih-alih menyediakan permukiman
sehat untuk semua lapisan masyarakat di Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda justru
hanya berfokus pada sektor permukiman bagi masyarakat Eropa dengan mewujudkan kawasan
permukiman yang ekslusif.
Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah
permukiman kolonial lebih terencana dibandingkan pada masa VOC dengan mempertimbangkan
faktor infrastruktur permukiman, serta arsitektur yang lebih adaptif dengan kondisi iklim dan
lingkungan lokal. Meskipun demikian permukiman kolonial tersebut masih mempertahankan pola
grid dan bersifat eksklusif terpisah dari permukiman etnis lain.
E. Perkembangan Pembangunan Permukiman Kolonial di Indonesia dari Masa ke Masa
Dari ulasan sebelumnya dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan
dalam prinsip pembangunan permukiman kolonial di Indonesia pada masa VOC dan Pemerintah
Kolonial Belanda yang diakibatkan perbedaan orientasi serta visi misi dari dua lembaga tersebut.
Perbedaan tersebut mampu mempengaruhi wujud dari arsitektur permukiman kolonial. Dari
kajian teori diketahui bahwasanya orang-orang Belanda pada masa VOC belum ada keinginan
untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Sehingga metode penerapan arsitektur Eropa di
Indonesia pada masa VOC dinilai lebih mengedepankan keamanan dan sesuai dengan pengetahuan
yang dimiliki melalui metode transplantasi tanpa memperhatikan kesesuaian terhadap iklim dan
lingkungan setempat.
Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Dari kajian
literatur diketahui bahwasanya keinginan untuk melakukan kolonialisasi terhadap Indonesia mulai
ada pada masa ini, dan hal ini berpengaruh pada keinginan untuk menetap dan membangun dalam
jangka waktu yang lama. Metode penerapan arsitektur Eropa atau Belanda di Indonesia pada masa
ini dinilai lebih memperhatikan kesesuaian terhadap iklim dan lingkungan setempat dengan lebih
mengedepankan metode adaptasi demi mendapatkan kenyamanan selain keamanan.
Selanjutnya, dari kajian literatur kita dapat mengetahui bahwasanya permukiman kolonial
di Indonesia dimulai dari permukiman di dalam benteng yang dibangun oleh VOC, permukiman
tersebut dapat berkembang menjadi permukiman di daerah sekitar benteng jika perdagangan di
suatu daerah dikatakan maju sehingga menarik banyak pedagang VOC untuk datang di daerah tersebut. Sehingga menurut beberapa literatur lain, benteng sering disebut juga sebagai salah satu
cikal bakal suatu kota kolonial. Lebih lanjut dari kajian literatur yang dilakukan, penulis menduga
bahwasanya permukiman di dalam benteng tersebut sifatnya merupakan permukiman temporer
yang didirikan dalam rangka menunjang fungsi perdagangan. Bentuk arsitektur permukimannya
tidak khas karena hanya menyesuaikan wujud dari arsitektur benteng itu sendiri. Selanjutnya,
karena daya tampung di dalam benteng dirasa tidak lagi memungkinkan, maka pedagang-pedagang
Belanda bagian dari persekutuan dagang VOC yang datang belakangan sebagai akibat dari adanya
monopoli perdagangan yang menguntungkan Belanda menggunakan lahan di sekitar benteng
untuk membangun huniannya. Arsitektur yang berkembang untuk permukiman di sekitar benteng
adalah relatif menyerupai arsitektur hunian yang ada di Belanda. Belum adanya keinginan untuk
menetap dalam jangka waktu yang panjang tampaknya mempengaruhi keinginan Belanda untuk
tidak mempelajari dan menggunakan arsitektur lokal yang relatif lebih sesuai untuk iklim dan
lingkungan setempat. Selain tentunya alasan keterbatasan sumber daya.
Dari beberapa sumber kajian literatur diketahui pula bahwasanya diakhir masa VOC
muncul suatu bentuk permukiman yang dibangun secara mandiri oleh orang-orang Belanda yang
terletak di luar benteng. Permukiman tersebut dikenal dengan istilah landhuis, suatu bentuk
permukiman yang terintegrasi dengan area pertanian atau perkebunan sebagai penyedia
komoditas dagang. Dalam membangun landhuis, proses adaptasi terhadap iklim maupun
lingkungan setempat mulai diterapkan dalam merancang rumah tinggal untuk orang-orang Eropa
atau Belanda. Lebih lanjut, jika dilihat dari foto-foto yang ada, proses adaptasi tersebut dilakukan
dengan cara meniru bentuk-bentuk arsitektur lokal yang sudah ada sebelumnya.
Masa Pemerintahan Kolonial Belanda merupakan era baru bagi pembangunan permukiman
kolonial di Indonesia. Keinginan untuk menetap dan menguasai Indonesia memunculkan orientasi
untuk membangun. Salah satu yang dikedepankan sebagai modal awal pembangunan adalah
adanya jalur transportasi yang terencana untuk memperlancar arus barang, jasa, dan manusia.
Oleh karena itu kemudian muncullah kebijakan untuk membangun jalan pos besar yang
menghubungkan hampir seluruh kota di pantai utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dan jalur
transportasi kereta api yang menghubungkan daerah-daerah pesisir dengan daerah pedalaman di
bagian tengah dan selatan Pulau Jawa. Selain itu,darianalisis yang telah dilakukan sebelumnya
diketahui bahwasanya pembangunan jalan raya pos dan jalur transportasi kereta api ada kaitannya
pula dengan beberapa kebijakan politik yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seperti
memperlancar pelaksanaan dari cultuurstelsel, serta mendorong munculnya agrarischewet, dan
decentraliewet karena dengan adanya jalur transportasi darat yang relatif komplit untuk masa itu
maka daya dukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk daerah pesisir maupun
pedalaman relatif sama sehingga menjadi daya tarik bagi investor. Dari kajian literatur diketahui
pula bahwasanya pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, pembangunan
permukiman kolonial mulai dirancanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan perencanaan
maupun rencana pengembangan kota. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan
pemukiman tidak didukung oleh kemampuan finansial Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena
itu maka dibentuklah sistem kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan
permukiman kolonial guna mewujudkan keinginan untuk membangun suatu kawasan khusus
permukiman yang lebih baik dan terjangkau di luar kota dimaksudkan untuk merespon masalah
kesehatan dan kesesuaian dengan iklim dan lingkungan setempat.
Untuk mempermudah memahami penjabaran mengenai perbandingan antara
pembangunan permukiman kolonial Belanda pada masa VOC (1602 - 1799 M) dan Pemerintah
Kolonial Belanda (1800 - 1942 M) penulis mencoba mengilustrasikannya pada Tabel. 2 seperti
berikut :Permukiman kolonial pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda memiliki beberapa
karakteristik. Yang pertama adalah permukiman kolonial dibangun di kawasan yang terpi sah dari
permukiman etnis lain dan memiliki teritori yang jelas. Hal ini selaras dengan Silas (2005) yang
menyatakan bahwa permukiman pribumi atau yang akrab disebut sebagai kampung cenderung
berkembang secara organik mengisi ruang-ruang kota tanpa batas-batas yang jelas. Yang kedua
adalah permukiman untuk orang-orang Eropa atau Belanda dibangun dengan pendekatan logis
formal, hal ini diindikasikan dengan bentuk permukiman yang cenderung grid dan fasilitas publik
yang relatif lengkap pada masanya. Seperti yang dijelaskan oleh Soekiman (2011) bahwasanya
warga kulit putih merupakan warga kelas pertama yang mendapatkan keutamaan dalam banya hal,
salah satunya adalah fasilitas publik. Selain itu, dengan menggunakan pola grid maka
pembangunan infrastruktur permukiman yang disediakan oleh pemerintah akan lebih efektif serta
efisien.
Dalam perjalanannya, pembangunan permukiman pada masa penjajahan Belanda di
Indonesia memiliki dua buah pendekatan berbeda yang dapat dikategorisasikan berdasarkan
pelaku. Pada masa VOC, belum terdapat perencanaan permukiman bagi orang-orang Eropa atau
Belanda yang dikarenakan orientasi utama VOC adalah berdagang, sehingga melahirkan
pandangan bahwasanya hunian adalah fasilitas pendukung yang sifatnya sementara. Permukiman
dibangun di dalam atau disekitar benteng yang lebih mengutamakan keamanan, arsitektur hunian
pun belum beradaptasi dengan kondisi iklim dan lokasi setempat serta cenderung
mentransplantasikan bentuk arsitektur hunian yang ada di Belanda. Hal ini berbeda dengan masa
Pemerintahan Kolonial Belanda, orientasi utama yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap
Indonesia melahirkan pandangan bahwasanya orang-orang Belanda akan tinggal di Indonesia
dalam waktu yang lama, maka diperlukan permukiman yang aman dan dapat beradaptasi dengan
kondisi iklim dan lingkungan setempat agar tercipta rasa nyaman.
Terdapat beberapa karakteristik dari pembangunan perumahan bagi orang-orang Eropa
atau Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah permukiman dibangun terpisah dari permukiman etnis lain, memiliki teritori atau batas yang jelas, memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap
dan tertata jika dibandingkan dengan permukiman untuk etnis lain, serta berbentuk atau
cenderung menggunakan pola grid untuk menata permukiman tersebut.















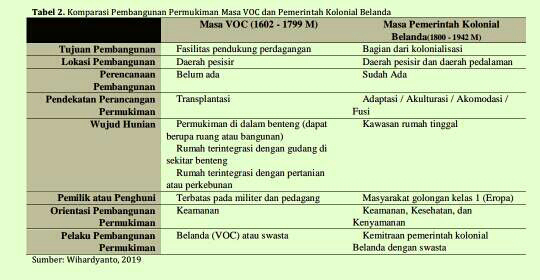



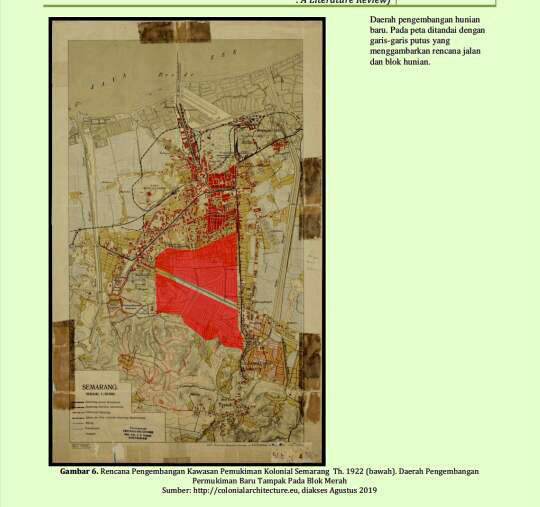



.jpg)






